
Kampung menyimpan kekayaan kultural. Kehadiranya bukan hanya sebagai permasalahan permukiman urban, tetapi lingkungan ini juga merupakan lokus sentral persebaran dan perkembangan kebudayaan subkultur Arek pada masa kolonialisme. Mereka, sebagai masyarakat periferal dari pembangunan kolonialisme, merancang kehidupan kebudayaannya di dalam kampung.
Celakanya, kekayaan kultural pada kampung tidak pernah dilihat oleh banyak orang. Fenomena ini selalu diposisikan sebagai permasalahan pembangunan. Akhirnya, itu menyebabkan kehidupan pada kampung hanya ditempatkan sebagai persoalan permukiman dan kemiskinan. Nalar tersebut, tentu saja, melipat realitas kultural yang terjadi di kehidupan arek kampung.
Nalar pembangunanisme ini sebenarnya juga warisan dari masa kolonial. Di masa awal kemunculan Kota Praja (Gemeente) Surabaya, pemerintah kolonial juga melihat bahwa kehadiran kampung adalah permasalahan permukiman. Arek kampung dianggap telah memadati permukiman yang berada di antara kompleks permukiman elit kelompok Eropa. Hal tersebut menyebabkan pemerintah kolonial harus segera mengambil sikap untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Kampung dalam Nalar Pembangunanisme
Perubahan administratif kota Surabaya pada 1906 menyebabkan pembangunan yang masif untuk kota ini. Pemerintah kolonial mulai membangun sistem pengairan air bersih, transportasi tram listrik, pelabuhan modern, dan lain sebagainya. Surabaya berubah menjadi kota modern ala koloni Belanda (Frederick, 1989). Kemajuan tersebut menciptakan permasalahan permukiman bagi Arek Surabaya sebab, ruang hidup mereka digantikan oleh perkotaan kolonial.
Masyarakat pribumi ini pun akhirnya memilih untuk menduduki ruang sempit di antara ruang kota Geemente Surabaya. Mereka menduduki kampung yang berada di gang sempit dan jalanan yang belum diaspal oleh pemerintah Kota Praja. Karena permasalahan tempat tinggal ini, pemerintah kolonial membangun suatu kompleks permukiman di daerah Keputran pada tahun 1929 sebab, Arek Surabaya mulai memadati permukiman di perkampungan tersebut.
Kasus pemindahan masyarakat kampung ke daerah permukiman di Keputran, (Geemente) Surabaya menunjukan bahwa permukiman mereka dilihat oleh pemerintah kolonial sebagai permasalahan pembangunan. Akhirnya, itu menyebabkan penyelesaian persoalan tersebut melalui relokasi permukiman masyarakat kampung. Itu menunjukan cara pandang pemerintah kolonial terhadap masyarakat pribumi.
Pada periode setelah masa kolonialisme, pendekatan yang sama pun masih digunakan. Kampung selalu dilihat sebagai permasalahan pembangunan. Kawasan tersebut selalu diandaikan sebagai lingkungan hidup yang terbelakang dan jauh dari pembangunan sebab, itu menyimpan suatu persoalan: kekumuhan; kemiskinan, dan keterbelakangan. Hal tersebut adalah cara pandang pemerintah setelahnya dalam melihat kampung.
Orde Baru, yang terkenal sebagai rezim pembangunan, turut mewarnai pemajuan kehidupan kampung. Sebab, Program pembangunan pada kampung pertama kali dilakukan pada tahun 1969, dan itu pun baru mendapatkan bantuan dari Bank Dunia pada tahun 1976 (Silas, 1992). Program tersebut memiliki tiga jenis bantuan yaitu: People Self-help projects, W. R. Soepratman projects, dan Urban Kampung Improvement Programme.
Adapun, program-program tersebut melingkupi pengembangan kampung seperti pembangunan akses jalan, selokan, fasilitas kesehatan, sekolah dasar, dan bak sampah guna pengelolaan kebersihan. Aktivitas tersebut tentu saja merujuk kembali kepada pendekatan yang digunakan oleh pemerintah kolonial dalam menangani persoalan tempat tinggal masyarakat pribumi, yaitu melalui pendekatan pembangunan.
Pola pembangunan, pada kampung, tentu saja, akan berimplikasi kepada cara pemerintah maupun para peneliti dalam melihat lingkungan hidup ini. Itu menghantarkan mereka, dalam melihat fenomena ini, sebagai salah satu objek pembangunan. Kampung selalu didudukan sebagai suatu entitas yang tertinggal dari kemajuan kehidupan modern. Kehadirannya haruslah diselamatkan dan diberi kemajuan ihwal kehidupan modern tertentu.
Secara lebih lanjut, Kawasan ini selalu dipandang sebagai pemukiman kelompok marjinal atau pinggiran. Masyarakat penduduk di dalam kampung pun selalu diposisikan sebagai masyarakat kelas bawah dan pemukiman marjinal. Kategorisasi perbedaan pemukiman marjinal pun selalu berlandaskan pada aspek-aspek, seperti: keamanan, rumah permanen dan temporal, harga jual murah/mahal, dan aksesibilitas yang mudah atau susah (Silas, 1989).
Di satu sisi, kehadiran kampung selalu melekat dalam nalar pembangunan, sedangkan di sisi lain kehadirannya, sebenarnya, memiliki dimensi kultural yang dilipat dalam nalar tersebut. Dimensi kultural inilah yang tidak pernah terangkat ke permukaan. Padahal, jika dilacak lebih jauh, kehadiran subkultur Arek juga merupakan fenomena kehadiran kampung di masa kolonialisme.
Meskipun kehadiran subkultur ini masih mengalami perdebatan ihwal pelacakan dan awal mulanya, tetapi periode yang pasti dapat ditandai untuk melacak keberadaanya adalah masa kolonialisme (1900-1942), yaitu transisi menjadi Kota Praja Surabaya. Sebab, periode tersebut memunculkan fenomena permukiman dan identitas masyarakat pribumi dalam konteks ini adalah kemunculan subkultur Arek.
Kampung sebagai Lokus Persebaran Subkultur Arek
Kemunculan subkultur Arek memang masih menjadi perdebatan di kalangan para akademisi. Ada peneliti yang menyatakan bahwa subkultur ini muncul semenjak masa 4-9 masehi. Letusan gunung Kelud, yang meletus sebanyak 22 kali, menutupi bengawan yang mengitari delta di wilayah subkultur Arek menjadi suatu kesatuan pulau (Abdillah, 2007). Fenomena tersebut, kelak, membentuk karakter Arek Surabaya.
Karena struktur daerah Surabaya, sebelum letusan Kelud tersebut, berbentuk delta, itu menyebabkan masyarakat Arek harus berbicara dengan keras. Kebiasaan tersebutlah yang melatar belakangi watak keras dari masyarakat Arek. Jadi, fenomena alam gunung Kelud menyebabkan pembentukan watak masyarakat Arek. Adapun, istilah Arek sendiri juga diambil dari istilah Jawa Kuna yang berarti sapaan untuk saudara atau adik laki-laki/perempuan.
Sayangnya, Belum ada bukti historis yang kuat untuk membuktikan tesis tersebut. Namun kehadiran subkultur ini dapat dilacak pada periode kolonialisme sebab, pada masa tersebut menciptakan suatu fenomena identitas bagi masyarakat pribumi, khususnya masyarakat subkultur Arek. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, peralihan Kota Praja menyebabkan permasalahan permukiman bagi pribumi.
Fenomena tersebut menyebabkan penciptaan batas permukiman antara kelompok elit Eropa dengan masyarakat Arek. Batas tersebut adalah batas antara perkampungan dan permukiman elit. Arek Surabaya kala itu, sebagai masyarakat periferal dari pembangunan kolonialisme, merebut ruang kota dengan cara menduduki daerah di antara perkotaan, yaitu kampung.
Akhirnya, itu menyebabkan masyarakat arek, yang notabene adalah masyarakat pendatang, membentuk identitas kulturalnya di dalam kampung. Jadi, kehadiran kota kolonial adalah kehadiran kampung yang menciptakan identitas subkultur ini. Masyarakat Arek tidak terbatas hanya pada kelompok etnik atau sosial yang terpadu. Mereka adalah para pendatang dan para pemukim yang memiliki nilai bersama, yaitu Arek Surabaya.
Hal tersebut mempengaruhi nilai Arek Surabaya yang identik dengan: keberanian, realisme, dan kemajuan material (Frederick, 1989). Karena mereka bukan suatu kelompok atau etnisitas tertentu, melainkan para pendatang yang berbagi nilai hidup sama, masyarakat Arek semakin memperteguh identitas kultural dan sosialnya di dalam kampung. Mereka membangun nilai-nilai budaya tersebut di dalam lingkungan tersebut.
Oleh sebab itu, kampung, faktanya, menyimpan kohesi baik sosial maupun kultural masyarakat Arek. Lingkungan ini membentuk identitas ke-Arek-an sebab, sebagai masyarakat pendatang dan disingkirkan ruang hidupnya oleh sistem kolonialisme, mereka membangun suatu bentuk identitas sosial-kultural bersama. Ini sekaligus menandai kemunculan subkultur Arek sebagai serpihan dari budaya induk Jawa.
Singkatnya, kampung adalah lokus sentral persebaran budaya Arek sebab, kemunculan subkultur ini berangkat dari fenomena permukiman di masa kolonialisme. Itu bukanlah hanya permasalahan permukiman saja, tetapi lingkungan ini juga menyimpan kehidupan kultural subkultur ini.



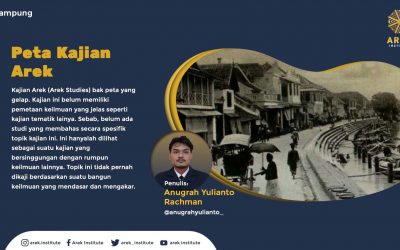
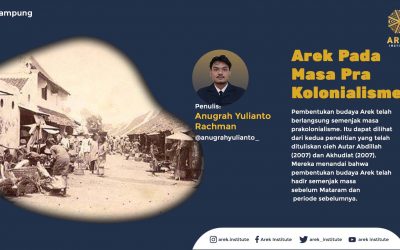

0 Comments