
Diky K. Arief | Mahasiswa Aqidah Filsafat Islam UIN Surabaya[]
Jula Juli bukan hanya sekedar bagian tradisi kidungan Jawa Timuran; ia adalah bentuk sastra yang merekam sejarah panjang manusianya. Dalam setiap tembang yang dilantunkan, terdapat cerita tentang keresahan, harapan, humor, kritik sosial hingga kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa, khususnya di Surabaya dan wilayah persebaran subkultur Arek.
Ragam Jula Juli
Jula juli dan ludruk selalu berkelindan dengan kesenian tradisional di Jawa Timur. Sebagai bagian dari pertunjukan ludruk, Jula Juli berperan sebagai pembuka atau iringan yang memberikan nyawa pada pementasan. Namun, Jula Juli tidak sepenuhnya bergantung pada ludruk sebagai medium penyampaiannya. Sebagai bentuk seni yang berdiri sendiri, Jula Juli dapat dilantunkan di luar pertunjukan Ludruk.
Untuk melacak kelindan antara Jula Juli dengan kesenian Ludruk, mari kita melihat sejenak sejarah kemunculannya. Ada beberapa versi yang mengisahkan kemunculan kesenian Ludruk dan Jula Juli. Awal mulanya kesenian ludruk berawal dari kreativitas seorang petani bernama Santik dari Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Pada tahun 1907, Santik bersama dua temannya yakni Pono dan Amir mengamen dengan Jula Juli, dari satu dusun ke dusun lain dengan riasan seperti perempuan yang dianggapnya lucu. Kemudian, mereka mengidungkan Jula-Juli yang bergaya humoris untuk menghibur masyarakat (Ismail, 2023).
Cerita lainnya berkata bahwa sebenarnya kesenian Ludruk sudah berkembang semenjak 1890, tetapi tidak dikenalkan oleh Santik, melainkan seorang pengamen yang bernama Gangsar. Ia berasal dari Desa Pandan, Jombang. Ini memiliki kesamaan cerita dengan Santik sebagai pionir kesenian Ludruk–pada masa itu masih dalam bentuk Lerok. Awal cerita, Gangsar pergi mengamen bersama dengan teman-temannya, dan ia bertemu dengan bayi yang sedang menangis sembari digendong seorang lelaki. Lalu, ia menjumpai bahwa lelaki, yang menimang anaknya tersebut, merias tubuhnya bak perempuan. Menurutnya, ia merias tubuhnya seperti seorang perempuan untuk mengelabui anaknya agar ia merasa seperti ditimang oleh seorang ibu. Dari situlah, Gangsar mengamen dengan merias diri layaknya seorang perempuan. Cerita tersebut juga menjadi salah satu alasan utama atas kemunculan tradisi travesti dalam kesenian Ludruk (Soenarno, 2023). Versi terakhir adalah perkembangan kesenian Ludruk yang dimulai di kota Surabaya.
Sayangnya, cerita-cerita tersebut hanyalah berfokus kepada kemunculan kesenian Ludruk. Sedangkan, cerita kemunculan Jula Juli belum banyak tergambarkan. Di sisi lain, perkembangan Jula Juli selalu melekat dengan perkembangan kesenian Ludruk. Seiring berjalannya waktu, Bentuk Jula Juli mulai melebarkan sayapnya untuk menjadi suatu kesenian yang tunggal–terlepas dari kesenian Ludruk. Kidungan, dalam Jula Juli, dilantunkan seperti permainan pantun dengan teknik vokal dengan iringan musik gending. Penuturannya pun menggunakan bahasa Jawa kasar-ngoko ala Jawa Timuran.
Seiring dengan perkembangannya, Jula Juli menyimpan suatu keidentikannya masing-masing di tiap wilayah Jawa Timur. Ia semakin melekat dengan konteks sosio-kultural masyarakatnya, seperti Jula Juli Surabaya-an, Pandalungan, Jombangan dan Malangan (Setiawan, 2017). Meskipun kesemuanya masih menyimpan pola pengiringan dan gaya musik yang serupa, tetapi setiap ragam Jula Juli tersebut memberikan suatu suasana dan karakter yang khas sesuai dengan daerah masing-masing, khususnya dalam aspek kebahasaan.
Keragaman Jula Juli melahirkan sejarahnya sendiri-sendiri dari tiap daerah. Ia merefleksikan kondisi budaya, sosial dan politik pada zamannya. Sebagai contoh, di Jombang berkembang gaya Jula Juli dengan laras slendro Pathet Wolu. Laras tersebut dilantunkan ketika pertunjukan Bapang Wayang Topeng Jatiduwur dipentaskan (Annur, 2022). Namun, belum ada baik bukti historis maupun cerita rakyat atas asal muasal perkembangan Jula Juli laras Slendro Pathet Wolu. Meski demikian, kesenian Wayang Topeng Jatiduwur sudah hadir semenjak masa Majapahit era Hayam Wuruk yang kemudian direvitalisasi kembali oleh Ki Purwo di Desa Jatiduwur Kesamben Jombang.
Selain di Jombang, pada sekitar tahun 2014 di Malang muncul sebuah gaya gending baru dengan tajuk Jula Juli Lantaran Gaya Malang. Laras tersebut dipelopori oleh Sumantri. Ia menciptakan gending tersebut sebagai respons terhadap keterbatasan pada gaya tembang sebelumnya, yaitu: macapat (Pamuji, 2017). Itu dapat dilihat dari perbedaan corak gendingnya. Dalam gaya Jula Juli Lantaran Gaya Malang, permainan gendingnya menonjolkan elemen tembang macapat, dengan pengolahan Kendang Kalih dan Gambayak (Pamuji, 2017). Ini sekaligus menandai karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh gending Jula Juli konvensional.
Berbeda dengan gaya Malangan atau Jombangan, Jula Juli Madura memiliki sejarah yang erat dengan dinamika sosial-politik pada masa kolonial Belanda. Jula Juli tersebut lahir sebagai anak zamannya. Ia dibentuk oleh kondisi akulturasi budaya Madura dan Jawa karena politik rasial kolonial Belanda. Catatan seorang Antropolog Belanda, yaitu: Huub de Jonge melegitimasi reproduksi atas pandangan stereotip pada masyarakat Madura. Ia menggambarkan orang Madura sebagai kelompok yang “terbelakang” dan “berwatak keras”, kedua label tersebut sekaligus menandai bias kolonial. Narasi tersebut mengokohkan cara pandang diskriminatif kolonialisme, dan itu juga, tentunya, semakin memperkuat stigma negatif yang melekat pada orang-orang Madura baik dari sudut pandang para penjajah maupun masyarakat daerah sekitarnya.
Kehadiran orang-orang Madura pun selalu diposisikan sebagai liyan. Suara-suara dari orang Madura lirih terdengar. Latar belakang historis stereotip itulah yang menyebabkan Jula Juli Madura memiliki keunikannya tersendiri untuk menyimpan perlawanan terhadap penundukan sistematis oleh sistem dan pengetahuan kolonial (Setiawan, 2017).
Hal itu juga terepresentasikan dalam kèjhungan gending Yang-Layang. sebuah kidungan khas Madura yang dipengaruhi oleh kidungan jawa dan perkembangan proses adaptif jula juli. namun bedanya terletak pada cengkoknya yang tinggi dan mendayu, yang menggambarkan karakteristik orang Madura yang tinggi dalam membela harga diri, lantang, blak blakan, dan suka merantau. (Mistortoify, 2015). seperti kèjhungan Yang Layang satu ini:
“Sampang roma sakè terjemahan: Sampang (punya) rumah sakit
Tuan dokter acapèngan potè tuan dokter memakai topi putih
Lo’ ghãmpang dhãddhi rèng lakè’ tidak gampang menjadi seorang lelaki
Mon lo’ pènter nyarè pèssè” jika tidak pandai mencari uang
(Mistortoify, 2015)
Melalui Jula Juli yang mereka ciptakan, mereka tidak hanya mengekspresikan identitas kebudayaannya, tetapi juga menunjukkan resistensi terhadap stereotip yang selama ini dilekatkan kepada mereka.
Persebaran orang-orang Madura di daerah tapal kuda juga menciptakan keunikan Jula Juli dengan gaya Pandulungan. Pendalungan adalah sebutan untuk masyarakat madura yang lahir di Jawa dan berakulturasi dengan budaya Jawa yang tinggal di daerah tapal kuda meliputi Jember, Situbondo, Probolinggo, dan Lumajang (Satrio, 2020)
Imigrasinya dapat dilacak pada abad 18 tahun 1870 ketika pemerintah kolonial belanda mengesahkan lebih banyak kebijakan undang undang agraria, yang membuka kesempatan perusahaan swasta untuk melakukan ekspansi ekonomi ke wilayah Jawa Timur. sehingga mulai bermunculan perkebunan karet, tebu, dan tembakau.Yang mana mereka mendatangkan para buruh dari madura berupah rendah untuk dipekerjakan (Akhiyat, 2023) Namun, tidak lain ini adalah siasat kolonial untuk melanggengkan praktik perbudakan. Sebab, Belanda mempekerjakan budak secara paksa sebagai tenaga kasar di perkebunan. Untuk menggarap lahan di Sumatera mereka mendatangkan budak dari Jawa. Dan untuk menggarap lahan di Jawa mereka mendatangkan budak dari Madura. Jadi, budak diambil dari wilayah yang dipisahkan oleh laut agar mudah dikendalikan (Setiawan, 2017)
Maka terjadilah akulturasi atas inklusifitas yang ada di wilayah tapal kuda yang kemudian melahirkan budaya khas, salah satunya jula juli Pandalungan/Pendalungan. Jula Juli pandalungan ini biasanya dihadirkan di dalam pentas kesenian Jaran Kencak, dan disisipkan ke babak Napel/Sumpingan. Dalam babak tersebut, seorang tamu menembangkan Jula Juli kepada tuan rumah, dan ia memberikan saweran kepada penari Remo sebagai penghormatan kepada tua rumah (Juwariyah, 2023).
Nura Murti dalam tulisannya mengumpulkan jula juli/ kèjhungan pandalungan di Kabupaten Jember yang memproyeksikan nilai akulturasi di wilayah tapal kuda (Murti, 2017) seperti yang satu ini:
“Tanem magik tombu sokon terjemahan: menanam biji asam tumbuh pohon sukun
tabing kerrep benyyak kalana gedhek(bambu) rapat penuh kalajengking
mompong gik odik koddhu parokon selagi masih hidup, harus rukun
ma’ olle salamet tèngka salana” agar selamat dalam bertingkah laku
Beragam jenis Jula Juli itu menunjukkan bahwa musik atau budaya tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk menyuarakan identitas, pandangan hidup dan bahkan respons ketidakpuasan terhadap situasi sosial yang dihadapi. Seperti seni tradisi lainnya, Jula Juli adalah saksi bisu bagaimana budaya menjadi arena perjuangan, di mana narasi-narasi tentang ketertindasan dapat diubah menjadi nyanyian yang menginspirasi dan mempersatukan berbagai macam kondisi hidup manusia.
Peran Jula Juli Sebagai Medium Perlawanan Sosial dan Propaganda
Dalam periode kolonialisme, Jula Juli berkembang menjadi sarana kritik sistem kolonialisme Jepang. Bumbu-bumbu satir ditambahkan ke dalamnya. Misalnya, dalam salah satu kidungan termasyhur milik Cak Durasim menggambarkan kritik terhadap penjajahan Jepang yang semakin memperburuk keadaan masyarakat pribumi sebagaimana dikutip pada artikel milik Setiawan (2021):
“Pagupon omahe dara
Melok Nippon tambah sengsara
Tuku klepon dhuk stasiun
Melok Nippon gak oleh pensiun”
Dua bait pertama tersebut juga tertulis pada pusara Cak Durasim yang ada di makam Tembok Gede Surabaya. Seakan menjadi sebuah pengingat bahwa seni dan budaya lokal, seperti Ludruk dan Jula-juli, memiliki fungsi sebagai sarana perlawanan. Jula Juli dihadirkan sebagai suatu sarana untuk menantang status quo pada masa itu.
Selain sebagai alat kritik sosial, Jula Juli juga digunakan sebagai media propaganda. Pada era demokrasi terpimpin 1959-an, partai politik sering memanfaatkan seni ini untuk menyampaikan pesan ideologis dari berbagai macam kelompok partai. Ini bisa dibuktikan dengan banyaknya partai politik yang mempunyai badan otonom yang mengurusi kesenian di dalamnya. Adapun, partai-partai yang memiliki lembaga kebudayaan adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mempunyai Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Masyumi yang mempunyai Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI), dan Partai Katolik yang mempunyai Lembaga Kebudayaan Indonesia Katolik (LKIK) (Susanto, 2017)
Banyaknya aliran politik serta ideologi yang dibawa oleh masing-masing partai membuat kebudayaan menjadi arena pertarungan gagasan dan pengaruh. Seni dan sastra, sebagai bagian dari kebudayaan, sering kali dijadikan medium untuk menyampaikan pesan-pesan ideologis, baik secara terang-terangan maupun tersirat. Bahkan, memunculkan anggapan bahwa “siapa yang menang, dialah yang berhak menulis sejarahnya” (Susanto, 2017).
Tak terkecuali pada kesenian Jula Juli maupun ludruk. Menjamurnya kesenian dan kelompok Ludruk di Jawa Timur justru dijadikan sarana propaganda partai politik yang menyebabkan terbentuknya dua kubu besar: Ludruk pendukung PKI dan Ludruk pendukung PNI, yang bahkan ketika kedua kubu ini tampil di panggung yang berdekatan, tak jarang mereka saling beradu gagasan melalui Jula Juli (Setiawan, 2021).
“Budal tandur, muleh njaluk mangan “Jumat legi nyang pasar genteng
Godonge sawi, dibungkus dadi siji Tuku apel nang Wonokromo
Ayo dulur, podho bebarengan Merah putih kepala banteng
Nyoblos partai, partai PKI” Genderane dr. Soetomo”
Kidungan Juli Juli tersebut adalah salah satu contoh bagaimana seni tradisional dimanfaatkan oleh partai politik untuk menyampaikan pesan ideologisnya secara subtil. Dengan gaya bahasa yang merakyat dan ritme yang akrab di telinga masyarakat Jawa Timur, propaganda politik disisipkan dalam syair-syair kidungan. Dalam hal ini, Jula Juli bertransformasi menjadi sarana komunikasi politik yang efektif, menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang mungkin tidak terbiasa dengan narasi politik formal. Meskipun begitu, kidungan dan kesenian ludruk yang berporos pada PKI, mulai meredup karena meletusnya kejadian 30 September. Peristiwa tersebut menandai titik senyap dan hilangnya kesenian Ludruk di panggung pertunjukan nasional (Setiawan,2021).
Sebab kala itu, Orde Baru tidak hanya menumpas PKI secara fisik, tetapi juga menghegemoni budaya yang diasosiasikan dengannya. Film Pengkhianatan G30S/PKI buatan orba disebarkan, buku-buku yang dianggap mengandung ideologi kiri dilarang dan ditarik dari peredaran, dan seni tradisional dijinakkan orba untuk mengarahkan karya sastra yang menampilkan cerita-cerita yang “aman” (Restu,2020). Salah satunya adalah ludruk. Ludruk, sebagai salah satu bentuk seni rakyat yang erat dengan narasi kerakyatan dan perlawanan, dianggap berbahaya. Di masa itu, ludruk ataupun Jula Juli yang merupakan bagian dari ludruk sempat kehilangan suaranya.
Revitalisasi Jula Juli di Era Kontemporer
Di tengah perkembangan budaya dari barat dan timur sekarang, tradisi ini menghadapi tantangan untuk tetap relevan di tengah arus modernisasi. Nama Cak Kartolo, maestro Ludruk Suroboyoan yang melegenda sering disebut sebut telah berperan signifikan dalam merevitalisasi Jula-juli agar tetap hidup dan dapat diterima oleh masyarakat masa kini.
Cak Kartolo merekam pertunjukan Ludruknya dalam bentuk kaset, yang kemudian tersebar luas ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Ia dikenal luas berkat penyampaian jula juli dengan gaya humornya yang sarat akan dagelannya. Dalam setiap rekamannya, ia selalu diiringi oleh grup karawitan Sawunggaling (Mukaromah, 2018).
Selain grup Sawunggaling dengan Cak Kartolo-nya. Di masa yang bersamaan, Cak Sulabi dengan grup ludruk Budhi Wijaya juga mulai unjuk gigi akan popularitas jula juli Suroboyan-nya. seperti jula juli berikut ini:
“Mulone jok gampang dulur peno dipecah belah
mundhakno sing seneng kaum penjajah
sopo sing salah dulur kudu podo ngalah
supoyo persatuan kito gak gampang blubrah”
Bahkan, Jula Juli mencoba untuk menemukan kembali bentuknya dalam permasalahan yang lebih mutakhir. Sebagai contoh, dalam dunia pendidikan, Jula Juli dimanfaatkan untuk mengajarkan nilai-nilai moral, sejarah hingga keterampilan sosial. Salah satu contohnya adalah kidungan ini:
“Sugeng enjang salam literasi
Anak-anakku sayang kabeh sing tresnani
Ayo belajar gawe mbangun negeri
Iki wawasan tekan sekolah yo dipelajari (Primaniarta, 2022).”
Melalui Jula Juli tersebut, bentuk kesenian tidak hanya mengenalkan kembali identitas budaya Jawa Timur kepada generasi muda, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun karakter dan memupuk kesadaran sosial. Oleh sebabnya pelacakan kembali perihal nilai dan pengetahuan yang tersimpan di dalam Jula Juli dapat menjadi suatu arkeologi pengetahuan budaya lokal di dalam subkultur Jawa Timur.
Daftar Pustaka
Ismail dan Asih Widiarti, “Pentas Ludruk yang Menolak Mati,” TEMPO Publishing, 2023.
Aris Setiawan, Suyanto Suyanto, dan Wisma Nugraha Ch. R., “Jula-Juli Pandalungan dan Surabayan Ekspresi Budaya Jawa-Madura dan Jawa Kota,” Resital: Jurnal Seni Pertunjukan 18, no. 1 (2017): 1–12
Aris Setiawan, “Kidungan Jula-juli in East Java: Media of Criticism and Propaganda (From The Japanese Occupation Era to The Reform Order in Indonesia),” Harmonia: Journal of Arts Research and Education 21, no. 1 (7 Juni 2021): 79–90.
Muhammad Akbar Darojat Restu Putra, “Membaca Lagi ‘Kekerasan Budaya,’” Islam Bergerak (blog), 2020
Gita Primaniarta dan Heru Subrata, “Development of Kidung Jula-Juli as a media for children’s literacy,” Premiere Educandum : Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran 12, no. 2 (2022): 1–13
Bima Atyaasin Annur, Setyo Yanuartuti, dan I. Nengah Mariasa, “Characteristics of Gending Jula-Juli Laras Slendro Pathet Wolu in The Bapang Dance Jombang Jatiduwur Mask Puppet,” Virtuoso: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Musik 5, no. 2 (2022): 142–47.
Iska Aditya Pamuji, “GARAP GENDING JULA-JULI LANTARAN GAYA MALANG,” KETEG: Jurnal Pengetahuan, Pemikiran, dan Kajian Tentang “Bunyi” 17, no. 2 (2017): 69–79.
Sonarno, Sejarah Ludruk (Semarang: Mutiara Aksara, 2023.).
Anik Juwariyah, “The Study of Panji Culture in the Pandalungan Sub-ethnic, East Java Review: Jaran Kencak Performing Art,” Atlantis Press, 2023.
Dwi Susanto, Lekra VS Manikebu (Sejarah Sastra Indonesia periode 1950- 1965) (Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service), 2017).
Axzella Raudha Mukaromah, “Proses Kreatif Cak Kartolo dalam Jula-Juli” (skripsi, Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2018).
Prakrisno Satrio, Suryanto Suryanto, dan Bagong Suyanto, “MASYARAKAT PENDALUNGAN (Sekilas Akulturasi Budaya di Daerah ‘Tapal Kuda’ Jawa Timur),” Jurnal Neo Societal 5, no. 4 (2020): 440–49.
Akhiyat dan Amin Fadlillah, “SEEKING THE HISTORY OF PENDALUNGAN CULTURE: A DISTINCTIVE STUDY OF LOCAL CULTURAL HISTORY IN THE HISTORY AND ISLAMIC CIVILIZATION PROGRAM OF UIN KHAS JEMBER,” Jurnal As-Salam 7, no. 2 (22 Juli 2023): 276–99.
Zulkarnain Mistortoify, “ONG-KLAONGAN DAN LÈ-KALÈLLÈAN ESTETIKA KÈJHUNGAN ORANG MADURA BARAT” (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2015).
Fitri Nura Murti, “Pandangan Hidup Etnis Madura dalam Kèjhung Paparèghân,” Istawa : Jurnal Pendidikan Islam 2, no. 2 (2017).


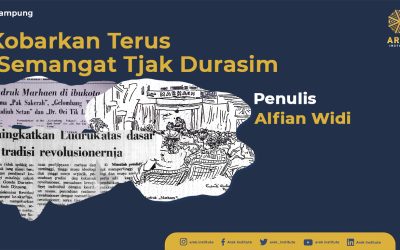
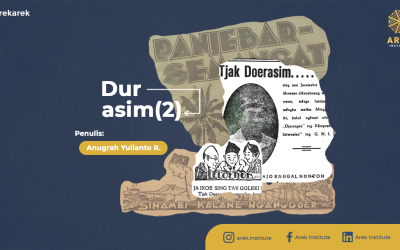
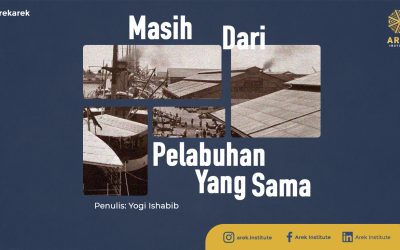

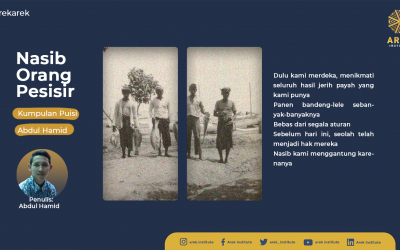
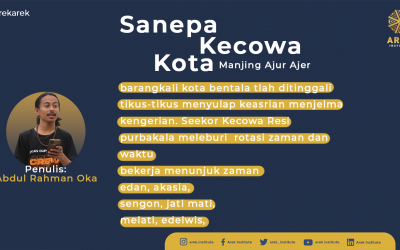
0 Comments