
Kolonialisme telah membentuk struktur kota Surabaya. Salah satunya adalah aspek ruang hidup. Penciptaan struktur kota tersebut menyebabkan munculnya batas antara ruang kota dengan kampung. Pembatasan ruang tersebut sangatlah berpengaruh pada kemunculan Arek Surabaya. Fenomena itu, misalnya, dapat dilihat dalam karya milik William H. Frederick yang berjudul “Pandangan dan Gejolak Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)” (1989).
Frederick, dalam buku tersebut, melakukan pelacakan hal-ihwal sejarah kota Surabaya. Pelacakan tersebut dimulai pada tahun 1906 sebab, pada episode tersebut, kota ini mengalami sistem desentralisasi akibat dari kebijakan politik etis. Karena sistem tersebut, Pemerintah kolonial mengubah struktur kota ini menjadi Gemeente (Kota Praja).
Celakanya, kota Surabaya, yang telah berubah menjadi Gemeente, justru semakin menghadirkan ketimpangan bagi Arek Surabaya kala itu. Ketimpangan tersebut hadir dari pembagian kelompok antara orang Eropa dengan pribumi (inlander). Itu menyebabkan munculnya hak khusus bagi warga Eropa. Meskipun Arek Surabaya dan warga Eropa hidup di dalam satu batas kota yang sama, tetapi warga pribumi tidak memiliki haknya sebagai warga kota yang setara.
Di sisi lain, akibat dari peralihan sistem pemerintahan tersebut, kota Surabaya mengalami arus modernisasi, dalam pembangunan kota, yang sangat kencang seperti pembangunan: pelabuhan modern, sistem pemurnian air bersih, transportasi tram listrik, dan jalan beraspal. Di satu sisi, Arek Surabaya, sebagai warga kota, justru menjadi “orang luar” (outsider). Sebagai contoh, mereka bermukim pada kategori tanah yang berbeda dari orang Eropa.
Perbedaan kategori tanah tersebut dapat dilihat dari ruang hidup miliki orang Eropa. Kategori tersebut muncul dari perbedaan antara pemukiman Elit Eropa dan pribumi. Daerah Darmo, sebagai contoh, adalah bentuk kompleks perumahan elit milik orang Eropa. Daerah tersebut dibangun dengan sangat layak oleh pemerintah kolonial, seperti adanya kebun binatang, jalan-jalan yang beraspal dan lebar, serta perumahan mewah. Sedangkan, Arek Surabaya harus menduduki ruang hidup di antara perkotaan tersebut.
Tidak seperti orang Eropa, Arek Surabaya menduduki kategori tanah yang berbeda. Mereka harus bermukim pada wilayah yang berada di antara perkotaan dan tidak terjamah pembangunan dari Gemeente. Daerah tersebut, pada akhirnya, diberi istilah kampung. Pribumi harus membangun peradaban dan kebudayaan mereka sendiri di dalam lingkungan tersebut.
Sementara, konsep kampung memang memiliki kemiripan dengan istilah seperti desa, tetapi, faktanya, keduanya memiliki perbedaan. Konsep kampung, dalam pandangan Frederick, memiliki kohesi sosial dan kepadatan penduduk yang berbeda dengan desa. Dalam konteks ini, ia berusaha menunjukan hal-ihwal keterikatan sosial di perkampungan. Kohesi tersebut berlandaskan pada latar belakang Arek Surabaya.
Bagi Frederick, Arek Surabaya tidak terdiri dari kelompok etnik atau sosial yang terpadu. Melainkan, mereka adalah para pendatang dan pemukim yang sama-sama tertarik dengan satu pandangan dan tradisi, yaitu keberanian, realisme, dan kemajuan material. Pembedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kohesi sosial di kampung, tetapi itu juga ditandai dengan adanya perbedaan ruang hidup antara kampung dan kota.
Perkampungan, yang berada di tengah kota Surabaya, secara langsung berbatasan dengan ruang perkotaan di Surabaya. Batas tersebut nampak dan sangat jelas, yaitu tembok besar, jalanan yang diaspal, atau bangunan-bangunan besar di pemukiman orang Eropa. Seluruh benda fisik tersebut telah menciptakan pemisahan antara ruang perkampungan dengan perkotaan. Itu sekaligus menandai bahwa tata ruang kota ini menciptakan pembatasan ruang hidup.
Dalam kasus tertentu, misalnya, pada tahun 1929, Arek Surabaya diberi ruang hidup di daerah Keputran. Pemerintah kolonial melihat bahwa kehidupan masyarakat kampung sudah semakin membludak dan padat, maka masyarakat pribumi harus diberikan ruang hidup yang lebih layak. Namun kepadatan penduduk tersebut tidak bisa dikalahkan dari hutan beton di Surabaya, seperti restoran, toko, hotel, dan rumah-rumah besar milik orang Belanda.
Kasus pemukiman Keputran telah membuktikan bahwa hubungan antara perkampungan maupun perkotaan telah menciptakan pembatasan yang terlihat (tangible-border). Itu sekaligus menandai kehidupan Arek Surabaya yang berada di ruang periferal. Bahkan pada tahun 1921, pemerintah Belanda sebenarnya sudah memiliki kesadaran untuk memindahkan warga kampung dari pusat perkantoran dan pemukiman Belanda ke daerah yang lebih terpinggirkan.
Penciptaan batas ruang hidup antara kampung dan kota dalam kasus Keputran adalah bentuk kemunculan Arek Surabaya yang berlandaskan pada relasi biner kota/kampung. Kehadiran batas-batas tersebut, seperti hutan beton di antaranya, telah menciptakan suatu stereotip atas masyarakat Arek yang hidup di dalam kampung.
Oleh sebab itu, Arek Surabaya, dalam penelitian Frederick, hadir dari penciptaan batas ruang hidup kota kolonial. Mereka adalah subjek liyan dalam konteks pembangunan kota Surabaya yang pada saat itu dikuasai oleh kolonialis Belanda. Perkampungan adalah wilayah “tertinggal” atau “ terpinggirkan” di tengah-tengah kemajuan kota ini. Ini sekaligus menandai bahwa istilah Arek Surabaya hadir dari stigma atas kehidupan perkampungan.
Singkat kata, kemunculan Arek Surabaya sebenarnya hadir sebagai patologi sosial atas konsekuensi struktur kota yang dibangun oleh kolonialisme. Hal tersebut menyebabkan Arek Surabaya menempati ruang sempit di antara perkotaan, yaitu kampung.

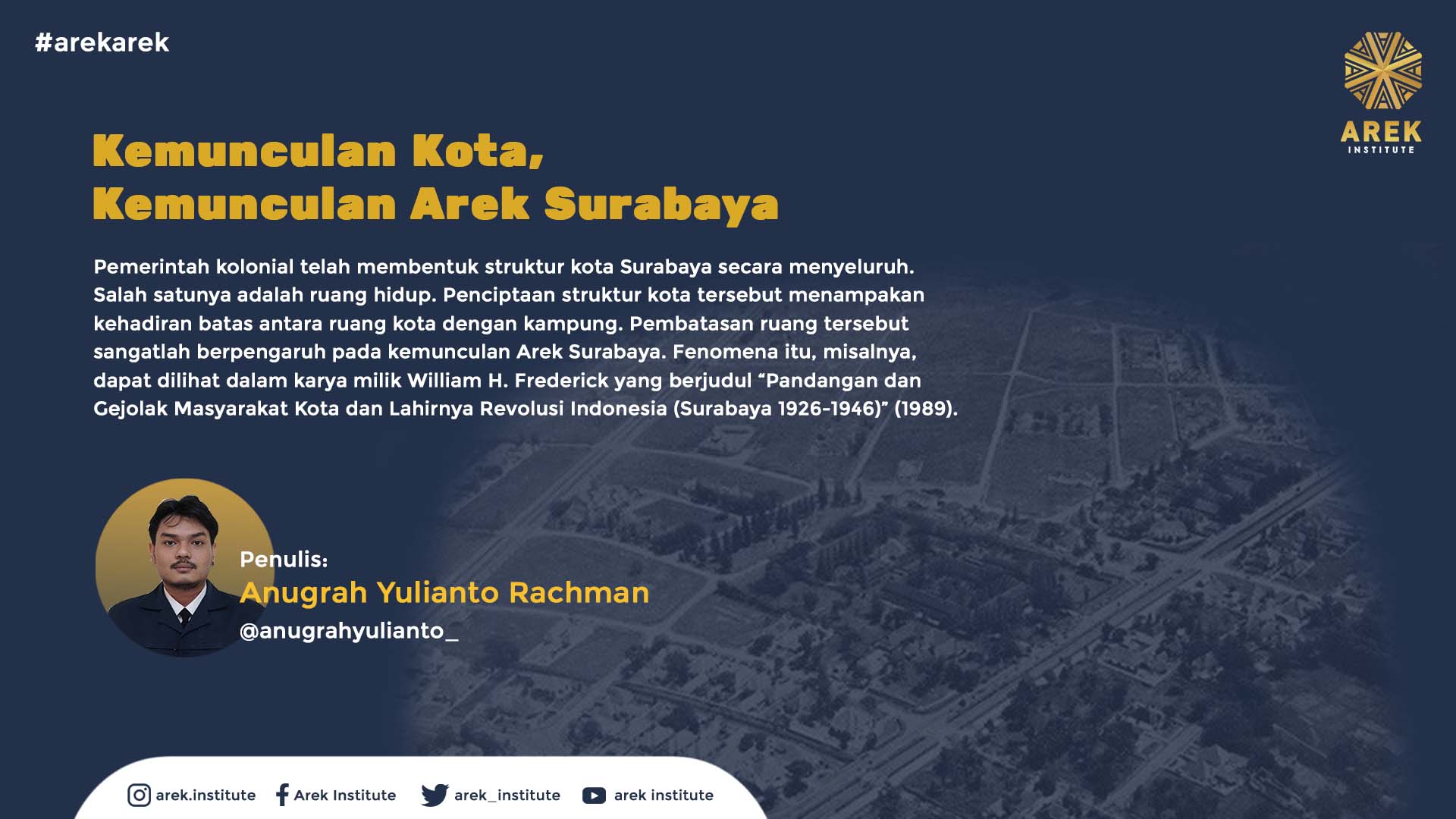

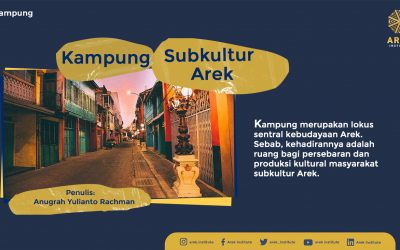
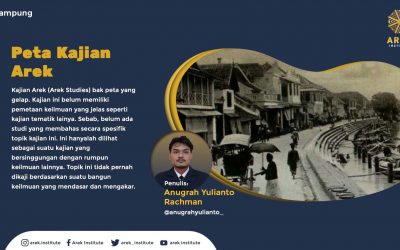
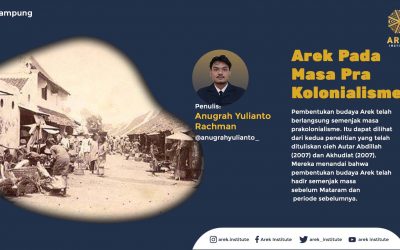
0 Comments