
Anugrah Yulianto Rachman–Nugi. Peneliti Arek Institute.
Peneliti maupun penulis Indonesia selalu menandai masa pra kolonialisme sebagai periode awal pembentukan budaya Arek. Itu dapat dilihat melalui dua tulisan yang berusaha melacak pembentukan budaya ini pada episode tersebut. Tulisan pertama adalah tulisan milik Autar Abdillah yang berjudul “Hibriditas Pertemuan Budaya Jawa Arek” (2007) dan karya kedua milik Akhudiat yang berjudul “Budaya Arek” dalam bukunya “Masuk Kampung Keluar Kampung” (2008).
Dalam artikel milik Autar, ia ingin membuktikan bahwa nilai-nilai Arek sudah muncul semenjak periode 1037-1468. Itu dibuktikan dengan fenomena alam yang membuat perubahan lanskap geografis di wilayah sebaran budaya Arek. Sebab, pada kisaran periode tersebut, gunung Kelud pernah meledak sebanyak 22 kali. Ledakan tersebut memiliki dampak kepada wilayah sebaran budaya Arek, yaitu Surabaya.
Ledakan tersebut menyebabkan, Surabaya kala itu, tertutup lahar dingin dari letusanya. Autar menampilkan peta Surabaya yang pernah digambarkan oleh Faber bahwa, awalnya, Surabaya adalah daerah yang berbentuk gugusan pulau atau delta. Akibatnya, letusan gunung tersebut menyebabkan delta, yang dipisah oleh sungai, tertutup dan menjadi suatu kesatuan. Perubahan lanskap tersebut turut mempengaruhi terbentuknya watak Arek Surabaya.
Watak, yang telah tercipta dari lanskap geografis tersebut, adalah karakteristik masyarakat Arek yang terkenal keras, lantang, dan pemberani. Watak tersebut muncul dari bentuk kepulauan atau delta dari wilayah subkultur ini. Sebab, kondisi geografis lingkunganya, yang terpisahkan dengan sungai, masyarakat Arek sudah terbiasa untuk berbicara dengan keras dan lantang. Hal tersebut turut membentuk watak atau karakteristik budaya Arek.
Watak budaya Arek, menurutnya, tidak hanya disebabkan karena fenomena alam, tetapi juga dipengaruhi oleh sapaan akrab yaitu Arek atau Rek. Ia berusaha melacak berdasarkan istilah Arek yang berasal dari Bahasa Jawa Kuna. Baginya, istilah tersebut muncul dengan kata dasar Ari, yang memiliki arti adik laki-laki, adik perempuan, bahkan orang yang bukan kerabat.
Selain itu, istilah Ari tersebut juga memiliki keterkaitan dengan kata benda Kawi yang berarti adhi, aryi, ari-ari, aruuman. Ternyata, istilah Ari juga tersimpan dalam kebahasaan Kawi. Tidak berhenti di situ, ia juga melihat perubahan istilah Arek yang terjadi pada istilah tersebut. Dalam Jawa Kuna, Ari-Ika atau arika berubah makna menjadi Arek. Namun memiliki arti yang sama, yaitu sedulur (ari-ari riko).
Artinya, pola sapaan, dalam subkultur Arek, sudah mengandung makna persaudaraan. Itu semakin dikuatkan dengan semangat kebersamaan dalam subkultur ini. Bagi Autar, nilai tersebut ditunjukan dengan ketika seorang datang bertamu, maka ia akan dipersilahkan seperti di rumah sendiri. Nilai tersebut tidak hanya terkandung pada sapaan akrab Arek, tetapi itu juga tersimpan dalam bentuk lain, seperti Sinoman Suroboyo.
Di sisi lain, pelacakan yang dilakukan Autar, faktanya, juga mendapat respons dari Akhudiat. Akhudiat berusaha melacak proses terbentuknya budaya Arek dalam periode sebelum penaklukan Mataram. Sebab, Surabaya, sebagai lokus sentral sebaran budaya Arek, pernah dipengaruhi oleh kehadiran Raden Rahmat (Kanjeng Sunan Ampel). Itu ditunjukan dari relasi politis dalam keluarga Sunan Ampel.
Bibi Sunan Ampel, yaitu Darawati, memiliki kedekatan dengan Prabu Kertawijaya—penguasa Majapahit. Karena kedekatan bibinya dengan penguasa Majapahit, ia diberi amanat untuk mengamankan kawasan Ampel Denta di pesisir Utara Surabaya pada abad 15. Dari situlah, ia mendapatkan sebutan Sunan Ampel. Sekaligus daerah tersebut menjadi lokus sentral islamisasi di Surabaya.
Kehadiran Sunan Ampel, dalam rangka mengamankan daerah tersebut, ternyata, memiliki pengaruh bagi perkembangan budaya Arek pada periode tersebut. Sebab, Surabaya, sebagai daerah yang dikuasai Majapahit, juga mendapatkan serapan nilai-nilai dari kultur kerajaan tersebut. Kultur tersebut adalah ciri bahasa yang tidak memiliki hierarkis.
Majapahit mengenalkan kepada budaya Arek tentang bentuk bahasa yang egalitarian. Kebahasaan tersebut memiliki kedekatan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Arek. Hal tersebut juga memiliki kemiripan dengan pola ajaran Islam pada periode Sunan Ampel. Sebab, ketika mengenalkan islam di Jawa, masyarakat lebih dikenalkan dengan corak kebahasaan Arab dalam bentuk Arab Pegon (Arab Gundul).
Pola kebahasaan yang egalitarian, dalam cara pengajaran islam melalui Arab Gundul, memiliki irisan dengan proses islamisasi di budaya Arek. Itu menunjukan bahwa terbentuknya kebudayaan Arek juga telah terbentuk semenjak periode sebelum penundukan Mataram. Masuknya Sunan Ampel juga memberikan implikasi terhadap budaya ini. Dampak tersebut adalah dampak percampuran Islam dengan Budaya Arek.
Karena kedekatan nilai bahasa tersebut, budaya Arek memiliki dampak yang dahsyat dalam kehidupanya. Dampak tersebut adalah terciptanya perbedaan karakteristik masyarakat di dalam budaya Arek. Perbedaan tersebut ditandai dengan segregasi masyarakat Arek, seperti Arek Lor-loran (masjid dan makam Ampel) dengan Arek Kidulan (Wonokromo). Keduanya mencirikan ciri karakteristik kehidupan masyarakat putihan maupun abangan.
Di satu sisi, berdasarkan proses islamisasi tersebut, Akhudiat berusaha membuktikan bahwa periode sebelum penundukan Mataram juga memiliki dampak terhadap pembentukan budaya Arek. Itu ditunjukan dari pelbagai fenomena islamisasi dan segregasi budaya Arek pada periode tersebut. Di sisi lain, Autar Abdillah berusaha membuktikan pembentukan budaya ini pada periode 1037-1468. Kedua orang tersebut saling mengisi ruang yang beririsan.
Oleh sebab itu, Kedua penelitian tersebut cukup memberikan gambaran hal-ihwal masa pembentukan budaya Arek pada periode pra kolonialisme. Keduanya saling memberikan penguat dan gambaran pada kajian Arek (Arek Studies). Itu sekaligus menunjukan bahwa pembentukan subkultur Arek telah berangsur jauh semenjak periode tersebut.
Singkatnya, Arek, sebagai suatu budaya, telah membentuk dirinya jauh sebelum fenomena kolonialisme. Pembentukanya dipengaruhi oleh pelbagai macam fenomena, seperti fenomena alam, kebahasaan, bahkan islamisasi.



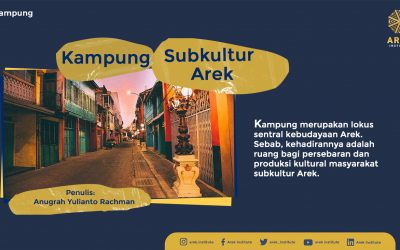
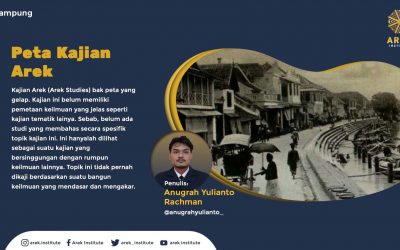

0 Comments