Artikel ini adalah tulisan dari Yogi Ishabib yang pernah diterbitkan dalam buku “Surabaya: City Within Kampung Universe” dengan judul asli “The Pigeon Race in Surabaya–When The Three Meanings of Kukila Interconnect”.
“Husy, Kau yang terlalu percaya pada segala yang serba Belanda.
Lima syarat yang ada pada satria Jawa: wisma, wanita, turangga, kukila, dan curiga.
Bisa mengingat?”[1]
Nukilan dialog di atas berasal dari percakapan Ibu dan Anak yang merupakan tokoh utama dalam salah satu roman termasyhur karya raksasa sastra Indonesia: Pramoedya Ananta Toer. Pesan Ibu kepada anaknya yang bernama Minke dalam roman itu dimaksudkan agar sang anak tak hanya melihat geliat zaman dari sisi Barat (Eropa) dengan segala capaian modernitas yang diembannya, tapi juga menengok kembali konsep menjadi manusia bajik berbudi luhur yang berasal dari sari-sari kehidupan berbudaya di tempat ia hidup dan tumbuh: Jawa.
Jawa memiliki konsep yang menarik untuk menjelaskan bagaimana menjadi seorang Manusia Jawa seutuhnya—tahu jati diri, lingkungan, dan laku hidupnya—yang bernama Satria Jawa. Untuk menjadi seorang Satria Jawa dibutuhkan lima syarat utama yaitu; wisma (rumah), wanita (wanita/istri/pendamping hidup), turangga (kuda/kendaraan/medium untuk mencapai tujuan), kukila (burung/hewan peliharaan/kegemaran akan sesuatu), dan curiga (sikap waspada/senjata). Menjadi Manusia Jawa yang utuh, menariknya, tak melulu berisi tentang nasihat atau pedoman yang menganjurkan segalanya musti serius karena konsep menjadi manusia bajik berbudi luhur ala Jawa menyediakan kelonggaran berupa pengakuan terhadap hal yang bersifat klangenan.[2]
Muncul pertanyaan, mengapa burung (kukila) yang dijadikan metafor untuk menjelaskan kegiatan berdasarkan kegemaran/ketertarikan terhadap sesuatu? Jawabannya bisa sangat beragam, tapi saya mencoba menganggit Jangka Jayabaya[3] yang menyatakan bahwa burung diandaikan sebagai sosok yang terbang bebas yang kemudian hinggap dan berpindah-pindah dari pohon yang satu ke pohon lainnya, seperti kebebasan manusia untuk memilih kesenangan/kegemaran terhadap sesuatu. Burung (kukila) juga digunakan oleh Jayabaya sebagai penanda zaman; zaman di mana segalanya serba tak menentu (kala kukila).[4] Keadaaan serba tak menentu ini adalah mualim kapal yang membantu kita untuk mengarungi pasang surut gelombang sikap moral dalam merespon kegiatan berdasarkan kegemaran terhadap sesuatu—hingga menjadi budaya—dengan segala batasan-batasannya. Dalam hal ini, saya mencoba membahas adu balap merpati[5] sebagai ritus kebudayaan yang melekat di Surabaya, yang dalam perjalanannya hingga hari ini mengalami pelbagai macam respon dan sikap yang serba tak menentu sesuai dengan kecenderungan zaman dan moral hukum. Adu balap merpati menarik dibahas karena memiliki kompleksitas pengertian kukila; sebagai pengertian harfiah yang berarti burung, sebagai kegiatan yang melibatkan kegemaran terhadap sesuatu (klangenan), maupun sebagai penanda zaman.
(Kukila) Sebagai Burung
Terdapat sebuah foto di Album Perang Kemerdekaan 1945-1950 terbitan Badan Penerbit Almanak RI, foto di album itu adalah awetan seekor merpati pos bernama “Letnan”. Sebuah keterangan yang tertera di foto itu berbunyi begini “Karena ketangkasan dan kecerdikannya, merpati pos ini telah dijadikan penghubung antara sebuah pos pasukan Tentara Republik Indonesia dengan pos Tentara Republik Indonesia lainnya di medan pertempuran.”[6]
Cerita legendaris merpati itu berasal dari Indonesia pada masa perang kemerdekaan di daerah Komando Ronggolawe Lamongan/Bojonegoro dengan front Surabaya di tahun 1946. Di antara kecamuk perang, beberapa tentara NICA-Belanda melihat seekor merpati terbang tak keruan, naik-turun seperti sedang dijemput ajal. Benar saja karena si merpati terbang dalam kondisi hampir kehilangan dua sayapnya lantaran terkena peluru yang memang sengaja dilontarkan untuk menghabisi nyawanya. Ia—si burung merpati pos gagah bersimbah luka itu—membawa pesan bagi komandan Tentara Republik Indonesia tentang situasi medan perang dan rahasia musuh. Konon, ia mati tepat di depan komandan Tentara Republik Indonesia yang dituju dan berhasil membawa pesan penting itu. Pasca kejadian heroik itu, tubuh si merpati diberi penghormatan terakhir dan diabadikan di museum dengan diberikan pangkat militer letnan anumerta. Sejak saat itu si merpati mendapat nama “Letnan”.
Cerita merpati bernama Letnan ini memiliki kadar heroisme yang sama dengan beberapa nama merpati pos legendaris di masa-masa perang seperti Cher Ami dan GI Joe. Cerita mengenai burung merpati yang sangat berguna sebagai pembawa pesan di awal-awal perang modern tampak seperti sebuah paradoks. Teknologi informasi yang coba dikejar oleh manusia di masa itu tak memiliki kelenturan fungsi seperti seekor merpati, lebih-lebih jika teknologi informasi pada masa kecamuk perang itu dihancurkan. Terhitung sejak dari Perang Dunia Pertama hingga Perang Dunia Kedua seperempat juta merpati telah digunakan sebagai pembawa pesan.[7]
Cerita-cerita tentang daya guna merpati sebagai pembawa pesan handal tentu didasari oleh kelebihan yang dimilikinya seperti; daya jelajah, daya ingat, kemampuan navigasi, komunikasi, serta sejarah panjang persinggungannya dengan manusia. Merpati adalah salah satu hewan paling awal yang didomestikasi oleh manusia.[8] Domestikasi burung merpati dipercaya berasal dari jenis merpati batu (Columba livia)[9] , yang selanjutnya hasil domestikasi itu berkembang menjadi 300 spesies merpati yang terdiri dari famili Columbidae dan ordo Columbiformes. Semakin menuju ke era modern, perbedaan variasi dan ciri-ciri bawaan merpati adalah salah satu yang terbanyak dari semua jenis burung yang ada di dunia.[10] Domestikasi burung merpati yang semula dilakukan sebagai sumber makanan berkembang menjadi upaya-upaya peningkatan kemampuan yang berhubungan dengan kecepatan untuk balapan dan daya ingat untuk pembawa pesan. Sampai hari ini, pengembangbiakkan burung merpati yang dilakukan oleh manusia memiliki tujuan utama untuk; balapan dan homing (sporting), konsumsi daging (utility), dan pameran (fancy).[11]
Domestikasi yang dilakukan manusia atas merpati adalah salah satu capaian sejarah peradaban manusia—sebab dilakukannya aktivitas itu membuat kehidupan manusia menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Merpati boleh saja tak secepat alap-alap[12] yang ditakuti sekaligus dipuja oleh petani dalam budaya masyarakat agraris Jawa, tak secerewet burung kicauan terkenal macam cucak rowo-murai-pleci-kacer, juga tak secerdik sekaligus menjengkelkan seperti gagak. Tapi, yang jelas, pesan tak akan sampai jika tak melalui kaki merpati, dan tak akan ada tepuk sorai orang-orang yang menengadahkan kepala ke atas jika tak untuk melihat merpati menukik tajam menuju ke kandang—sebuah gaya dan manuver yang menjadi salah satu ilham sempurna bagi pionir dunia penerbangan.
(Kukila) Sebagai Klangenan
Sejak domestikasi terhadap merpati pertama kali tercatat dalam peradaban Mesopotamia pada tahun 5000 SM, merpati memiliki jangkauan peran yang beragam di masing-masing kebudayaan dan peradaban. Narasi tradisional di beberapa kebudayaan dunia merespon domestikasi ini sebagai salah satu kemenangan manusia sebagai “mahluk unggul” atas semua mahluk yang hidup di bumi dengan menyatakan bahwa adalah hak manusia untuk menundukkan segala yang ada di bumi sesuai dengan kehendak dan kebutuhannya. Tak salah bagi manusia sebagai “mahluk unggul” untuk mendomestikasi merpati sebagai salah satu mahluk yang mendukung kehidupan manusia karena fungsi, sifat, dan kelebihan yang dimilikinya. Tapi ada juga beberapa narasi tradisional yang menyatakan bahwa domestikasi merpati adalah simbol atas penundukan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi hasrat membangun peradaban.
Aesop, seorang pencerita fabel legendaris yang dipercaya hidup di era Yunani kuno (620-564 SM) memberikan metafora yang menarik atas domestikasi merpati sebagai cara manusia membentuk kebudayaan dan peradabannya melalui kerja-kerja penundukan atas mahluk lainnya. Di dalam kumpulan fabel Aesop terdapat dua cerita yang berhubungan dengan merpati. Pertama, merpati digambarkan sebagai sosok yang mewakili segala kebaikan yang karena kebaikannya ia layak hidup bebas. Cerita dimulai dengan kebaikan hati merpati menolong semut yang tergelincir dan hanyut oleh arus sungai yang deras. Kebaikan berbalas kebaikan dengan ditolongnya merpati oleh semut dari seorang pemburu. Si semut menggigit mata pemburu yang sudah siap membidik si merpati sehingga ia pun bisa hidup dan terbang bebas.[13] Kedua, merpati yang digambarkan sebagai simbol kesucian dan kemurnian hati, yang karena mewakili simbol itu membuatnya terjerat oleh keinginan manusia untuk memeliharanya. Cerita dimulai ketika seekor merpati yang merasa bahagianya bertambah-tambah karena selain hidupnya terjamin karena dipelihara oleh manusia, ia juga sedang menunggu anak-anaknya menetas dari telur yang ia erami. Datang seekor gagak, burung berwarna hitam kelam yang dianggap tak memiliki keindahan. Si gagak bertengger di sangkar indah si merpati. Si merpati tetap menyombongkan apa yang ia dapat hari ini dan kebahagiaan yang ia dapat dari anak-anaknya kelak. Si gagak malah tersenyum dan berkata, “My good friends, cease from this unseasonable boasting. The larger the number of your familiy, the greater your cause of sorrow, in seeing them shut up in this prison-house.”[14]
Di Indonesia, ada banyak ungkapan yang berhubungan dengan merpati yang maknanya bisa saling bertolak belakang antara yang satu dengan yang lain. Ungkapan “merpati tak pernah ingkar janji” adalah salah satu bentuk ungkapan tentang kesetiaan dengan pengandaian bahwa merpati (sang subyek) bisa saja terbang puluhan atau ratusan kilo hanya untuk kembali ke sarang dan pasangannya. Di saat yang sama ada juga ungkapan “bagai merpati di dalam sangkar” yang mengandaikan keterbelengguan melalui merpati (sosok yang terbelenggu) yang tak bisa terbang (kehendak bebas) karena dipelihara (domestikasi) oleh manusia (sosok yang membelenggu). Ada ungkapan yang mewakili paradoks macam “jinak-jinak merpati” yang mengandaikan bahwa setiap subyek memiliki paradoksnya sendiri; seekor merpati bisa saja jinak (hasil domestikasi) tapi sewaktu-waktu ia bisa saja terbang dengan sendirinya tanpa kembali (mengejar kebebasan, atau secara pesimistik adalah lawan kata “setia”, kata yang pada ungkapan sebelumnya melekat erat pada sosok merpati). Beragamnya respon terhadap merpati adalah sesuatu yang menarik yang mengandaikan bahwa sosok merpati—dengan segala macam sifat, lambang, dan fungsinya—mewakili dualisme antara kebajikan-keburukan, kejayaan-kemalangan, sakral-profan, atau tipisnya garis batas antara keduanya.
Garis batas seperti saya sebut di atas memiliki kesamaan konteks dengan konsep kukila dalam artiannya sebagai klangenan. Untuk menjadi Manusia Jawa yang utuh maka manusia justru diberi kelonggaran; kelonggaran terhadap pilihan hidup, kelonggaran untuk tak menekan habis kesenangan diri agar tunduk kepada tatanan dunia yang serba serius. Konsep kelonggaran ala Jawa ini menarik karena memberikan kesempatan manusia agar memiliki waktu, bukan untuk dikuasai oleh waktu. Kukila dalam artiannya sebagai klangenan adalah garis batas antara dunia serius yang mensyaratkan kerapatan aktivitas pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan dunia yang serba cair, sebuah dunia yang memberikan kesempatan untuk menikmati kebahagiaan yang berasal dari dipenuhinya hasrat kesenangan akan sesuatu—dalam hal ini adalah adu balap merpati.[15]
Kesenangan dari adu balap merpati biasanya didapatkan oleh penggemarnya melalui kecepatan terbang dan manuver tajam merpati saat menuju pegupon.[16] Keasyikan ini ditangkap dengan cukup jeli oleh salah satu penulis ternama di Indonesia; Suparto Brata. Melalui novelnya yang berjudul Mencari Sarang Angin, Suparto Brata secara spesifik menyebut adu balap merpati di kota Surabaya sebagai salah satu latar peristiwa. Adu balap merpati dalam novel itu disebut membuat para penggemarnya larut dalam kegembiraan hingga “Dibicarakannya hal-hal itu dengan asyik, ditirukan gaya terbang merpati dengan jari tangannya, ditirukan bunyi dua ‘thuk’ yang sangat berdekatan. Sangat indah dipercakapkan bersama”.[17]
Penggemar adu balap merpati, pada titik keasyikan tertentu bisa membedakan garis keturunan khusus dari perkembangbiakkan merpati. Garis keturunan khusus yang unggul dalam dunia adu balap merpati disebut trah jawara, sedangkan cara membaca garis keturunan khusus merpati melalui ciri fisiknya disebut katuranggan.[18] Beberapa orang menilai tak selamanya trah jawara menjadi jaminan seekor merpati akan benar-benar menjadi juara pada adu balap merpati selama merpati tak mendapatkan perawatan yang baik, tapi setidaknya trah jawara pada merpati memudahkan pemilihan dan perawatan khusus bibit merpati unggulan yang akan diterjunkan pada adu balap.
Cerita tentang keasyikan adu balap merpati membawa sebuah nama legendaris dari lomba yang diselenggarakan oleh klub adu balap merpati tertua di Indonesia. Nama merpati legendaris itu adalah Si Pecut. Si Pecut adalah juara kelas super derby untuk jarak tempuh 1000 km yang bisa ia tuntaskan dalam waktu 3 hari dengan kecepatan 650 meter per menit.[19] Cerita Si Pecut ini sama legendarisnya dengan merpati milik Yett Resdianto yang berhasil melewati empat selat (Selat Flores, Sumbawa, Lombok, dan Bali) dengan jarak tempuh 1600 km pada tahun 1988. Merpati milik Yett Resdianto yang bernomor cincin P-87-870560 itu menaklukkan ganasnya cuaca gunung dan badai selat dalam waktu 4 hari, lebih cepat daripada merpati Amerika yang menmpuhnya dalam waktu seminggu.
Lomba yang diikuti merpati legendaris Si Pecut dan merpati Yett Resdianto diselenggarakan oleh Lang-Lang Buana, klub adu balap merpati tertua yang ada di Indonesia. Cikal bakal Lang-Lang Buana sebagai komunitas adu balap merpati berawal dari kegemaran anggota militer dan saudagar Belanda memelihara burung merpati dan dijadikan aduan. Kumpulan anggota militer dan saudagar ini membentuk komunitas yang diberi nama Akbar Khan, anggotanya adalah orang-orang Belanda dan Indo Belanda di bawah kepemimpinan Meneer Kransier.[20] Setelah kemerdekaan, banyak anggota Akbar Khan yang kembali ke Belanda, koleksi merpati anggota Akbar Khan yang kembali ke Belanda itu dijual kepada orang-orang Indonesia. Beralihnya kepemilikan merpati dan bergantinya keanggotaan bersamaan dengan pergantian nama klub yang semula bernama Akbar Khan menjadi Lang-Lang Buana.
Lang-Lang Buana menjadi klub adu balap merpati resmi pertama di Indonesia yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Rubiyono Kertopati. Pada tahun 1962 Lang-Lang Buana terlibat di pelbagai ajang olahraga nasional maupun internasional seperti Ganefo (Games of the New Emerging Forces) di Jakarta, Asian Games, dan PON (Pekan Olahraga Nasional). Lang-Lang Buana hingga hari ini masih aktif dan tercatat menyelenggarakan adu balap merpati di kalender internasional acara PIPA (Pigeon Paradise)—sebuah rumah lelang merpati aduan yang berbasis di Belgia—yang selalu rajin menampilkan kejuaraan adu balap merpati di seluruh dunia. Baru-baru ini Lang-Lang Buana menyelenggarakan adu balap merpati kelas Derby dengan jarak 600 km di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 26 Agustus 2017.
Sementara itu di Surabaya, lomba balap merpati terakhir yang tercatat sebagai acara “resmi” adalah Kejuaraan Nasional Balap Merpati Anniversary Cup III yang dihelat pada tanggal 22 Agustus 2003 di daerah Sukolilo.[21] Kejuaraan balap merpati itu diselenggarakan oleh Persatuan Penggemar Merpati Balap Sprint Indonesia (PPMBSI) dengan harapan dapat dijadikan agenda nasional dan diikutsertakan dalam Pekan Olahraga Nasional, meski setelah diselenggarakannya acara itu balap merpati tak pernah benar-benar mendapat tempat di setiap acara olahraga skala nasional. Tak mendapatkan tempat di acara-acara olahraga skala nasional tak menyurutkan keinginan masyarakat untuk tetap melakukan balap merpati yang dilakukan di sekitar tempat tinggal. Di sisi lain, dengan tak mendapatnya tempat pada ajang resmi berskala nasional membuat balap merpati seolah-olah menjadi sebuah aktivitas pinggiran yang tak penting untuk dibahas tapi justru paling mudah dikenai stigma berdasarkan kaidah moral sepihak.
Adu balap merpati dipandang sebagai budaya pinggiran yang mewakili ekspresi negatif sebenarnya bukan hal baru, tetapi mengaitkannya semata-mata kepada persoalan moral tentu tak mengudar jalinan kusut masalah yang menyertai setiap penyelenggaraannya. Di satu sisi adu balap merpati memiliki nilai budaya yang sangat panjang seperti laiknya gelaran aduan apapun yang berhubungan dengan kecepatan. Di sisi lain, kecenderungan adu balap merpati—seperti kecenderungan pada tiap gelaran aduan yang sifatnya olahraga—rentan direbut oleh dunia bisnis pertunjukan (showbiz) yang tak hanya menyediakan segala macam kemeriahan, tapi juga ekspresi negatif, salah satunya adalah judi. Di titik inilah pentingnya upaya membuka kemungkinan akses informasi, literasi, dan infrastruktur pendukungnya dalam membaca gejolak budaya sesuai dengan konteks zamannya, bukan malah larut dalam penyematan predikat buruk kepada aktivitas klangenan macam adu balap merpati ini. Laiknya makna kukila sebagai klangenan yang sedari awal memberikan pilihan bagi manusia untuk memiliki waktu bukan dimakan oleh waktu, apabila klangenan macam adu balap merpati pada titik tertentu justru memakan waktu dan merenggut hidup penggemarnya hingga jatuh pada kubangan nasib buruk, maka saat itu juga aktivitas adu balap merpati tak bisa disebut klangenan.
(Kukila) Sebagai Penanda Zaman
Tersebutlah nama seorang pemberani yang begitu lantang melakukan kritik keras pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Ia tak bersenjata laiknya gambaran klise pahlawan kemerdekaan di Indonesia yang cenderung militeristik, bukan seorang panglima besar dengan darah bangsawan yang mengalir di tubuhnya, bukan pula seorang paderi yang menggelorakan semangat jihad. Adalah Gondo Durasim, seorang seniman dari kalangan rakyat jelata yang kerap berkeliling untuk mementaskan lakon melalui seni pertunjukan ludruk. Ia merintis pertunjukan ludruknya pada tahun 1931 hingga pengaruhnya dirasakan oleh rakyat sebagai penghibur kelas wahid di tengah kehidupan yang serba genting. Pengaruh itu yang konon dimanfaatkan oleh Dr. Soetomo untuk merekrut Gondo Durasim sebagai penyambung kesadaran atas ketertindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dan menyampaikan pentingnya persatuan, berdaulat sebagai negara yang bebas dari cengkeraman penjajah.[22]
Gondo Durasim yang kemudian lebih dikenal sebagai Cak Durasim tak henti melakukan sindiran-sindiran terhadap pemerintah kolonial melalui komedi dan kidung jula-juli[23] yang ia lontarkan di setiap pertunjukan ludruk yang digelarnya. Puncaknya, sebuah kidung jula-juli jenaka yang dilontarkan Cak Durasim sampai ke telinga pemerintah Jepang dan berhasil membuat pemerintah Jepang murka setelah tahu artinya. Kidung legendaris itu berbunyi, “Pegupon omahe doro, melu nippon tambah soro” yang memiliki arti; pegupon rumah burung dara (merpati), dijajah Jepang membuat keadaan semakin sengsara. Setelah kidung legendaris itu terlontar, Cak Durasim ditangkap oleh pemerintah Jepang pada tahun 1943 dan meninggal pada tahun 1944.[24]
Memelihara merpati (dara atau doro) di pegupon adalah budaya adu balap merpati di Surabaya[25], dan budaya ini dicuplik oleh seniman legendaris seperti Cak Durasim sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan. Pertunjukan ludruk biasanya merespon suatu kejadian sehari-hari sebagai bahan parikan yang dinyayikan dalam bentuk kidung jula-juli. Hal ini menandakan bahwa adu balap merpati sudah menjadi budaya yang lazim sejak zaman kolonial. Setelah zaman kolonial, budaya adu balap merpati semakin marak dilakukan oleh orang-orang Surabaya, baik melalui klub-klub adu balap merpati mapan macam Lang-Lang Buana maupun yang dimainkan oleh masyarakat kelas pekerja sebagai hiburan selepas bekerja.[26] Adu balap merpati yang dilakukan oleh kelas pekerja di Surabaya biasanya dilakukan pada sore hari dengan memanfaatkan ruang kota seperti perempatan jalan, lapangan, rel kereta api, dan area pemakaman. Adu balap merpati yang memanfaatkan lanskap kota ini disebut sebagai kenthongan.
Semaraknya adu balap merpati pasca zaman kolonial tak berlangsung lama, karena setelah itu berturut-turut adu balap merpati dianggap sebagai bagian dari budaya yang tak pantas dilakukan. Pada tahun 1965 adu balap merpati dilarang karena dicurigai oleh militer sebagai alat komunikasi orang-orang komunis untuk melawan pemerintah. Semua kegiatan yang berhubungan dengan merpati dilarang oleh pemerintah, bahkan klub adu balap merpati yang diketuai oleh militer macam Lang-Lang Buana tak luput dari pantauan militer. Pada waktu itu untuk melatih kemampuan terbang dan kecepatan merpati, pemilik merpati harus meminta dan mendapat izin dari jawatan perhubungan.[27] Sejak saat itu adu balap merpati kerap dipandang sebagai aktivitas orang-orang pinggiran yang berpendidikan dan berpenghasilan rendah, abangan, ajang judi, dan tak jarang juga dianggap sebagai budaya bawaan komunis.
Paradoks yang muncul kemudian adalah Walikota Surabaya, Kolonel Sukotjo, mengajukan permohonan izin kepada Menteri Sosial untuk melakukan pelegalan judi Lotto (Lotere Totalisator) untuk wilayah Kota Surabaya pada tanggal 9 Oktober 1967. Pada tanggal 15 Mei 1968 Surat Keputusan No. B. A. 5-4-44/71 terbit, pemerintah pusat melalui Menteri Sosial memberikan izin kepada pemerintah Kota Surabaya untuk menyelenggarakan lotto secara resmi untuk mendukung pendanaan PON ke VIII di Surabaya.[28] Dilegalkannya judi di Surabaya membuat aktivitas perjudian kembali marak, pertarungan yang muncul kemudian adalah antara judi resmi yang legal di mata hukum dan diselenggarakan oleh pemerintah dengan judi ilegal berdasarkan kebiasaan. Adu balap merpati menjadi unik karena aktivitas ini tidak berada di antara kedua jenis judi yang disebutkan di atas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 1981 disebutkan jenis-jenis perjudian antara lain:
- “Perjudian di Kasino antara lain terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Jackpot, Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar Paser, Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa-Hwe, Kyu-Kyu,
- Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar pasir atau bulu ayam pada papan sasaran yang tidak bergerak, Lempar Gelang, Lempar Koin, Kim, Pancingan, Menembak sasaran yang tidak berputar, Lempar Bola, Adu Ayam, Adu Sapi, Adu Kerbau, Adu Domba, Pacu Kuda, Karapan sapi, Pacu anjing, Hailai, Mahyong, erek-erek,
- Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Pacu kuda, Karapan sapi, Adu domba”[29]
Selanjutnya, adalah pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
- dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.[30]
Dua dasar hukum (PP 9/1981, pasal 303 ayat 3 KUHP) tak pernah benar-benar menyebut adu balap merpati sebagai tindak pidana perjudian. Meskipun begitu, aparat penegak hukum bisa mengategorikan adu balap merpati sebagai salah satu bentuk perjudian yang bisa sewaktu-waktu diberantas; pelakunya bisa ditangkap, diadili, dan dijebloskan ke penjara atas tuduhan tindak pidana perjudian. Berita-berita penangkapan pelaku adu merpati disertai penyitaan burung merpati dan pegupon di media mulai marak. Contoh penangkapan terhadap adu balap merpati sebagai perjudian di Surabaya baru-baru ini adalah di kawasan Karang Asem pada tanggal 2 Agustus 2017.[31] Penangkapan adu balap merpati ini berhasil menangkap 40 orang pelaku yang diduga terlibat pada perjudian adu balap merpati, adu ayam, togel, dan dadu. Biasanya pelaku yang diduga melakukan tindak pidana aduan—termasuk adu balap merpati—akan dikenakan hukuman maksimal 5 bulan penjara melalui proses pengadilan yang menyatakan bersalah kepada terdakwa tindak pidana adu merpati dengan catatan “Dengan tanpa ijin telah melakukan perjudian”.[32]
Suara-suara negatif tentang adu balap merpati yang beririsan dengan perjudian sejatinya tak abadi. Adalah Mayjen Pol M. Dayat, Kapolda Jatim tahun 1998, yang membela keberadaan adu balap merpati sebagai salah satu budaya yang memainkan peran penting bagi ekonomi kelas pekerja, bahkan bisa dijadikan sumber penghasilan bagi orang yang tidak memilki pekerjaan tetap (pengangguran). Mayjen Pol M. Dayat bersikukuh bahwa adu balap merpati harus ada sebagai bagian dari budaya meski di tahun itu gelombang protes dari masyarakat anti-judi yang tergabung dalam Forum 99 Ulama mulai mendesak pemerintah untuk menghentikan segala praktik judi di Jawa Timur.[33] Mayjen Pol M. Dayat beralasan bahwa adu balap merpati memiliki potensi untuk dikembangkan untuk meningkatkan geliat pariwisata, membuka lapangan pekerjaan, serta membuka peluang ekonomi berantai lainnya. Atas dasar itu Mayjen Pol M. Dayat menyelenggarakan Police Cup pada tahun 1998 sebagai atraksi pariwisata, upaya peningkatan ekonomi masyarakat, sekaligus kontrol terhadap adu balap merpati ilegal yang ada di kampung-kampung.[34] Pasca diselenggarakannya Police Cup, sudah jarang adu balap merpati yang difasilitasi oleh pihak kepolisian. Saat ini satu-satunya kegiatan adu balap merpati yang difasilitasi oleh kepolisian hanya Kapolres Cup Klaten yang diselenggarakan pada tanggal 9-11 Juni 2017 di desa Mlese, kecamatan Gantiwarno, kabupaten Klaten.[35]
Pasang surut gelombang sikap moral terhadap adu balap merpati mulai dari anggapan sebagai salah satu ajang olahraga bergengsi, simbol perlawanan untuk menolak penjajahan, tuduhan alat komunisme, hingga jatuh kepada ekspresi negatif macam judi adalah gejolak yang dialami adu merpati sebagai penanda zaman. Adu balap merpati seolah-olah menjadi penanda zaman dalam setiap perjalanan sejarah, menjadi saksi aktual yang harus siap ditimpa oleh pelbagai macam predikat yang mewakili gejolak zaman. Saya sengaja meminjam istilah dari Jangka Jayabaya tentang konsep zaman kala kukila; zaman di mana semuanya serba tak menentu. Adu balap merpati memiliki segala syarat terhadap segala ke-takmenentu-an. Adu balap merpati adalah penanda zaman yang bergolak dan kaburnya batas-batas konvensional kita terhadap segala persepsi oposisional; kebajikan-keburukan, kejayaan-kemalangan, legal-ilegal, sakral-profan. Adu balap merpati terus mengada, tak hanya sebagai budaya dan identitas, juga sebagai teks yang menghantui narasi moral hukum yang beririsan dengan narasi budaya di tiap perempatan jalan seperti laiknya merpati yang dilepaskan bocah-bocah kenthongan; terbang untuk kembali ke kandang sebagai yang menang atau yang kalah, atau memilih terbang tak kembali agar bebas istirah dari tempat satu ke tempat lainnya.
[1] Pramoedya Ananta Toer. Bumi Manusia. Jakarta: Hasta Mitra. 1980. Hal 463
[2] (Jawa) Klangenan : Kesukaan, kesenangan, kegemaran terhadap sesuatu
[3] Andjar Any. Jayabaya, Ranggawarsita, dan Sabda Palon. Semarang: Aneka Ilmu. 1976
[4] Ibid. hal 81
[5] Di Surabaya biasa disebut adu doro
[6] M.F. Mukthi. Legiun Merpati untuk Komunikasi. Majalah Historia. Artikel bertanggal Jumat, 3 Mei 2013. Bisa diakses pula di http://historia.id/modern/legiun-merpati-untuk-komunikasi
[7] Pigeons in War. The Royal Pigeon Racing Association. Bisa diakses di http://www.rpra.org/pigeon-history/pigeons-in-war/
[8] M. Thomas P. Gilbert dan Michael D. Saphir (Ed Claire Smith). Pigeon: Domestication dalam Encyclopedia of Global Archeology. New York: Springer. 2014. Hal 2
[9] Ibid. Selanjutnya, sebutan “pigeon” dalam bahasa Inggris yang berarti merpati berasal dari bahasa latin “pipio” yang berarti burung muda. Penyebutan pigeon umumnya digunakan oleh masyarakat yang menggunakan bahasa Inggris untuk menyebut merpati
[10] T. D Price. Domesticated Birds as a Model for The Genetics of Speciation by Sexual Selection. Genetica 116: 311-27. 2002
[11] History of Pigeon. Animal Science Journal No. 4H135. University of Wisconsin: 4-H Publication. 2004. Hal 9
[12] Sejenis Falcon, sebutan untuk burung pemangsa anggota keluarga Falconidae
[13] Aesop’s Fables. Shanghai: Comercial Press. 1922. Hal 66
[14] Ibid. hal 131
[15] Hampir serupa dengan konsep “waktu luang” yang dimiliki oleh kelas pekerja (yang memiliki kedekatan makna dengan maskulinitas) di Eropa. Konsep pemanfaatan “waktu luang” untuk klangenan bukanlah sebuah konsep monolitik mutlak yang hanya dimiliki oleh budaya Jawa
Bisa dibaca di artikel Martin Johnes. Pigeon Racing and Working Class Culture in Britain, c 1870-1950. Cultural and Social History, Vol. 4, Issue 3, hal 361–383
[16] Kandang. Di beberapa daerah di Surabaya biasa juga disebut bekupon
[17] Suparto Brata. Mencari Sarang Angin. Jakarta: Grasindo. Hal 116
Di dalam novel itu Suparto Brata menyebut nama-nama tempat biasa diselengggarakanya adu balap merpati di Surabaya seperti Kedungdoro, Embong Malang, Tegalsari, dan Kedungsari. Nama-nama tempat itu adalah jalan besar yang mengelilingi daerah Kampung Plemahan yang menjadi salah satu lokasi dalam novel Suparto Brata
[18] Katuranggan pada trah jawara merpati balap secara garis besar membahas spesifikasi ciri fisik yang meliputi; berat badan, postur, bentuk dan pangkal sayap,ukuran kepala, mata, kaki, bentuk dan ukuran paruh, tulang dada,dan ekor. Lebih lengkapnya baca Tabloid Agrobis Burung No.767, edisi Minggu Ketiga Februari 2015
[19] Inilah Merpati Pemenang Adu Cepat Bali-Jakarta. Koran Tempo. Kamis, 10 Oktober 2013. Bisa diakses di https://m.tempo.co/read/news/2013/10/10/108520878/inilah-merpati-pemenang-adu-cepat-bali-jakarta
[20] Lang-Lang Buana, Komunitas Merpati Tertua Indonesia. Koran Tempo. Jumat, 8 Maret 2013. Bisa diakses di https://m.tempo.co/read/news/2013/03/08/108465911/lang-lang-buana-komunitas-merpati-tertua-indonesia
[21] Surabaya Menggelar Lomba Balap Merpati. Liputan6 SCTV, 23 Agustus 2003, 09.10 WIB
[22] Partisipasi Seniman dalam Perjuangan di Propinsi Jawa Timur: Studi Kasus Kota Surabaya tahun 1945-1949. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1999. Hal 31-37
[23] Seni berpantun khas Jawa Timur. Bentuknya hampir sama dengan pantun Melayu yang memilki rima di tiap akhir kalimatnya
[24] Cak Durasim melontarkan kidungan itu di sebuah pertunjukan ludruk di Desa Mojorojo, Jombang. Menjadi pertunjukan terakhir Cak Durasim
[25] Memelihara di pegupon adalah salah satu cara paling mudah untuk membedakan merpati yang digunakan sebagai aduan dengan merpati yang hanya dipelihara biasa. Pegupon adalah kandang besar yang bisa menampung beberapa merpati. Bentuk pegupon berupa pondok kayu yang menjulang ke atas, fungsi utamanya adalah sebagai rumah bagi merpati sekaligus sebagai garis finis saat dilakukan adu balap merpati
[26] Purnawan Basundoro, dkk (ed). Tempo Doeloe Selaloe Aktoeal. Jogjakarta: Ar Ruzz Media. 2007. Hal 156
[27] Petikan wawancara Karna Tjendera dengan Koran Tempo. Lang-Lang Buana, Komunitas Merpati Tertua Indonesia. Koran Tempo. Loc cit
[28] Awalnya dikenal dengan nama Lotto Jatim, namun DPR-GR tidak menyetujui perederan lotto di seluruh Jawa Timur. Wilayah penyelenggaraan lotto dipersempit hanya di kota Surabaya saja berdasarkan Surat Keputusan Gubernur pada 4 April 1968 No. Gub/ 76/78. Bisa dicek di Arsip Kota Surabaya No. Definitif 909
[29] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981. Koleksi Arsip Nasional, Nomor Arsip 1536
[30] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht Staatsblad) Nomor 732 Tahun 1915
[31] Dibiarkan Polsek Tambaksari, Arena Judi Merpati Jl Karang Asem diobrak Polrestabes Surabaya. bisa dicek dan diakses di http://www.lensaindonesia.com/2017/08/02/dibiarkan-polsek-tambaksari-arena-judi-merpati-jl-karang-asem-diobrak-polrestabes-surabaya.html
[32] Saya menggunakan contoh putusan Nomor : 872/Pid.B/2012/PN.Jr. yang dikenakan kepada seorang tukang becak yang ditangkap dan diadili karena tindak pidana perjudian adu balap merpati. Bisa dicek di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di putusan.mahkamahagung.go.id
Untuk contoh putusan Nomor : 872/Pid.B/2012/PN.Jr. bisa diakses di http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=+budiman+bagon+judi+merpati
[33] Robbie Peters. Surabaya, 1945-2010. Neighbourhood, State and Economy in Indonesia’s City of Struggle. Singapore: NUS Press. 2013. Hal 131
[34] Ibid. hal 132
[35] Kapolres Cup Klaten Digeruduk Merpati Balap Luar Kota, Acara Puncak Minggu 11 Juni. Bisa diakses di http://burungnews.com/sragen-september-ceria-sragen-bc-agenda708.html?542


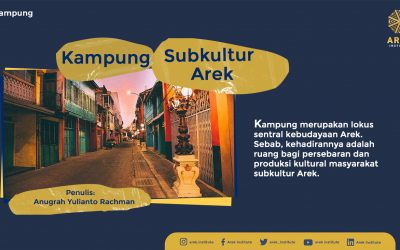
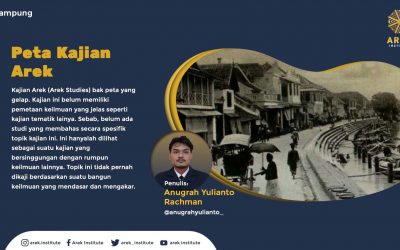
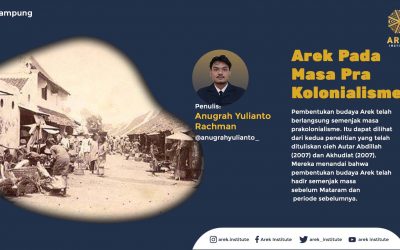

0 Comments