
Doni Rahma | Mahasiswa Antropologi FISIP Unair | Jejaring Peneliti Arek
Hampir 100 tahun lalu, tepatnya Pada 11 Maret 1917 di Surabaya, lahir sebuah gerakan bernama Djawa Dipa yang menentang praktik-praktik feodalisme pada kala itu. Menurut berbagai catatan Gerakan ini pertama kali diinisiasi di dua tempat yakni gedung Oost Java Bioscoop (sekarang menjadi gedung pertokoan di daerah Aloon-aloon Contong) dan Oost Java Restaurant.
Sejak awal diinisiasi, Djawa Dipa memang bertujuan untuk menyamaratakan penggunaan bahasa jawa dengan cara menghapus sistem hierarki-bahasa di dalamnya. Dengan kata lain unggah ungguh ing basa (tingkatan bahasa jawa ngoko-kromo) harus dihapus.
Kaum Kromo sebutan bagi lapisan masyarakat Jawa Bawah menjadi perhatian utama karena kesetaraan bagi mereka adalah hal terpenting. Selama ini hierarki dalam penggunaan bahasa Jawa hanya memperlebar jurang stratifikasi sosial dan memperkuat perlakuan tidak adil terhadap mereka (Thamrin, 2022).
Salah satu tokoh penting di balik lahirnya Djawa Dipa adalah Tjokrosoedarmo pemimpin SI afdeling Surabaya, arekSurabaya yang berasal dari Kampung Plampitan dan berlatar belakang dari golongan keluarga priyayi. Namun, berkebalikan dengan asal-usulnya, ia justru malah menjadi sosok yang vokal dalam menolak aturan penggunaan bahasa krama tersebut.
Baginya, tata bahasa yang penuh hierarki itu bukanlah alat komunikasi, melainkan tembok pemisah yang menindas serta dirasa hanya memberatkan untuk kaum Jawa. Hal ini sebagaimana terlihat dalam penggalan Gagasan radikalnya saat Tjokrosoedarmo berpidato dalam acara pembentukan komite Djawa Dipa yang turut dimuat dalam koran Sinar Djawa edisi 15 Maret 1917.
”…telah njata kita ketahoei, sampai saat ini, dan sampai zaman perobahan ini, atoeran bahasa Djawa ”kromo” itoe hanjalah membikin soesah kita Djawa sadja. Berlantaran atoeran bahasa Djawa ”Kromo” itoe tidak sedikit bilangannya…Maka ketjelakaan dan kesengsaraan pendjara itoe bagi kita boekan bangsa ”sastrawan” hanjalah lantaran soesahnja atoeran bahasa Djawa ”kromo” ada di moeka persidangan hakim”
Pada masanya Djawa Dipa nampak didukung oleh tokoh besar di dalamnya seperti Tjokroaminoto dari Sarekat Islam itu sendiri. Walaupun pada awalnya Tjokroaminoto tidak terlalu antusias terhadap kehadiran Djawa Dipa. Namun, ketika gerakan ini pelan-pelan meluas pada tahun 1918 serta semakin berkurangnya dominasi Tjokroaminoto di CSI membuat ia bergegas menghimpun kekuatan baru.
Djawa Dipa lantas diperjuangkan dan didorong untuk menjadi gerakan yang militan untuk memperbaiki ”mental budak” masyarakat Jawa (Siraishi, 1997). Sebagai sebuah gerakan, Djawa Dipa sering secara langsung menyampaikan berbagai seruan mengenai ajakan untuk mengurangi penggunaan bahasa Jawa ”Kromo”. Anjuran awalnya seperti merubah sapaan panggilan menjadi ”Wiro” Untuk laki-laki, ”Woro” bagi perempuan sudah menikah sedangkan yang belum dipanggil ”Liro” (Thamrin, 2022).
Lalu berkembang juga seruan untuk menolak ritual hormat yang sudah mengakar lama di dalam sistem birokrasi Hindia Belanda. Penghormatan tersebut mencakup perilaku sosial, aturan berpakaian, sistem bahasa bertingkat, gelar kehormatan. Orang Jawa diharuskan memperlakukan pejabat Belanda dengan cara berjalan membungkuk (Jongkok); menyapa pejabat kolonial dengan sebutan kanjeng tuan; melakukan duduk bersila di hadapan mereka; dan melakukan gerakan menempelkan kedua tangan ke bibir atas (sembah) setelah mereka berbicara (Der Meer, 2021).
Meskipun kehadiran Djawa Dipa disambut sangat antusias oleh masyarakat Jawa hingga menjadi pembicaraan di berbagai koran saat itu, kehadiran kelompok ini juga membawa konsekuensi bahwa eksistensinya juga turut diragukan dampaknya untuk menyamaratakan bahasa Jawa. Pandangan tersebut muncul dari golongan elit konservatif yang merasa kekuasaannya terancam karena hadirnya Djawa Dipa. Hal ini tampak, misalnya, dalam salah satu rubrik koran De Indier yang terbit pada 10 April 1917. Dalam rubrik tersebut, tidak jelas siapa penulisnya, namun dari tulisannya tampak adanya sikap skeptis terhadap kehadiran Djawa Dipa.
”De ngoko-questie houdt de gemoederen in de inlandsche wereld nog warm. Er is bereids een vereeniging gevormd onder den naam Djawa Dipa, die het ngoko zal trachten vereheffen tot algemeene tal op Java. Wij staan er zeer sceptisch tegenover!”
”Masalah ngoko masih menghangatkan perbincangan di dunia bumiputra (pribumi). Sudah terbentuk sebuah organisasi bernama Djawa Dipa, yang akan berusaha mengangkat ngoko menjadi bahasa umum di Jawa. Kami sangat skeptis terhadap hal itu!”
Lalu ada juga opini panjang Berjudul ”Djowo Dipo Contra Adat” ditulis oleh salah satu kepala distrik—tidak dijelaskan secara rinci daerah mana—yang dimuat dalam koran De Locomotief edisi 14 Juni 1921. Ia turut menyampaikan pendapatnya tentang kehadiran Djawa Dipa yang mulai meresahkan.
Menurutnya, gerakan Djawa Dipa sudah dianggap merusak wibawa para priyayi. Pejabat kolonial tersebut menilai sapaan informal seperti ”Kowe” kepada pejabat sebagai sebuah bentuk penghinaan terhadap adat dan struktur kekuasaan yang telah mapan. Walaupun ia juga tidak menyangkal perubahan nyata terjadi akan tetapi kesopanan tetaplah yang utama. Ia mencontohkan salah satu peristiwa saat seorang wedana didatangi oleh dua anggota Djawa Dipa.
”…De wedono liet zich niettemin door die woorden niet van streek brengen, bleef kalm en vroeg den heeren gemoedelijk in het hoog-Javaansch: ‘Sampean wonten perloe poenopo?’ (Wat is er van uw dienst?”
(Wedono tidak terganggu oleh kata-kata mereka, tetap tenang dan dengan ramah bertanya kepada para tamu dalam bahasa Jawa tinggi: ‘Sampean wonten perloe poenopo? ‘Ada keperluan apa?’)
“Een van de twee bezoekers antwoordde, natuurlek niet erg deftig en in zijn bijzonder ‘dialect’: Akoe arep toetoer marang kowee, wedono enz.” (Ik wil jou het volgende mededeelen enz.”
(salah satu dari kedua tamu menjawab, tentu saja tidak terlalu sopan dan dalam dialek” khasnya: ‘Aku arep tutur marang kowe, wedono’ (Aku ingin mengatakan sesuatu padamu, wedono, dan seterusnya))
”Toen werd het den wedono begrijpelijkerwijs te machtig en om zijn gramschap niet te uiten stond hij op en ging zijn huis binnen.”
”Lalu wedono, yang secara wajar merasa sangat tersinggung, bangkit berdiri dan masuk ke dalam rumahnya untuk menahan amarahnya.”
Terlepas dari itu semua Djawa Dipa sendiri memilih untuk tetap aktif bersuara. Lalu, untuk mempermudah penyebarluasan propaganda mereka, maka pada April 1921 akhirnya diterbitkan koran mingguan edisi pertama bernama ”Hindia Dipa” (Thamrin, 2022).
Jadwal penerbitan koran tersebut tampaknya mengalami percepatan dari jadwal yang direncanakan. Hal ini berbeda dari pemberitaan Nieuwe Rotterdamsche Courant pada edisi 22 Maret 1921 yang mengabarkan jika surat kabar ”Hindia Dipa” akan rilis akhir tahun 1921. Di sisi lain Hindia Dipa sebagai corong media Djawa Dipa memilih menggunakan Melayu-Jawa sebagai bahasa utama dalam koran mereka.
”De Oetoesan Hindia meldt dat het hoofdbestuur van de Djawa Dipo voornemens is ultimodezer een maleisch-Javaanasch weekblad, de Hindia dipo uit te geven onder redelie van Tirtodanoedjo, Srosardjono en Soetojomihardjo.”
(Oetoesan Hindia melaporkan bahwa dewan utama Djawa Dipo bermaksud menerbitkan mingguan berbahasa Melayu-Jawa, Hindia Dipo, pada akhir tahun ini, di bawah arahan Tirtodanoedjo, Srosardjono dan Soetojomihardjo.)
Bahasa Sebagai Alat Perlawanan
Selama abad ke-19, Belanda secara tegas telah mendoktrin diri mereka dalam masyarakat Jawa melalui proses perampasan budaya yang melegitimasi otoritasnya. Legitimasi kekuasan Belanda tersebut sangat bergantung pada pelestarian budaya kaum elit tradisional. Belanda sengaja menciptakan hegemoni budaya melalui pemanfaatan penerapan ritual ala Jawa.
Simbol-simbol kekuasaan seperti hierarki dalam bentuk berbusana, gaya hidup, bahasa, konsumsi, dan arsitektur itu lantas kemudian dipelihara oleh belanda (Der Meer, 2019). Menurut Geertz dalam bukunya Negara Teater turut menjelaskan bahwa kekuasan negara bukan hanya hadir dalam bentuk lembaga-lembaga tapi juga lewat simbol yang terus menerus diproduksi. Dengan kata lain simbol bukanlah perkara estetika semata, tetapi itu juga sekaligus menandai wujud kekuasan itu sendiri.
Lantas semua itu perlahan mulai bergeser, Awal abad ke-20 merupakan salah satu periode transformatif perubahan sosial dan budaya. Kebijakan politik etis oleh Belanda secara tidak langsung telah menciptakan kondisi bagi perkembangan gerakan pribumi yang menjadi kritis terhadap segala hubungan dengan bangsa kolonial yang sifatnya feodal (Der Meer, 2021). Dalam konteks inilah, sejarah mencatat bahwa di Surabaya juga pernah muncul gerakan radikal yang menentang dominasi negara berkaitan dengan hirarki bahasa. Seperti yang disampaikan J. P. Zurcher, meski adat tetap dijunjung, zaman telah banyak berubah. Rakyat Jawa dahulu bukan lagi rakyat Jawa masa kini. Mereka telah berkembang dan secara alami melahirkan semangat perlawanan.
DAFTAR PUSTAKA
Der Meer, A. (2019). Igniting Change in Colonial Indonesia: Soemarsono’s Contestation of Colonial Hegemony in a Global Context. Journal of World History, 30(4), 501–532.
Der Meer, A. (2021). Sweet Was the Dream, Bitter the Awakening: The Contested Implementation of the Ethical Policy 1901-1913. In Performing Power: Cultural Hegemony, Identity, and Resistance in Colonial Indonesia (pp. 48–76). Cornell University Press.
Districtshoofd. (1921, June 14). Djawa Dipa Contra Adat. De Locomotief.
Djawa Dipa. (1917, April 10). De Indier.
Geertz, C. (2017). Negara Teater: Kerajaan-Kerajaan di Bali Abad Kesembilan Belas. BasaBasi.
Java en Madoera. (1921, March 22). Nieuwe Rotterdamsche Courant .
Siraishi, T. (1997). Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926. Pustaka Utama Grafiti.
Thamrin, M. H. (2022). Djawa Dipa: Sama Rata, Sama Rasa, Sama Bahasa 1917-1922 (1st ed.). Komunitas Bambu.
Zurcher, P. J. (1920). De Indische Gids (Vol. 42). J. H. de Bussy.

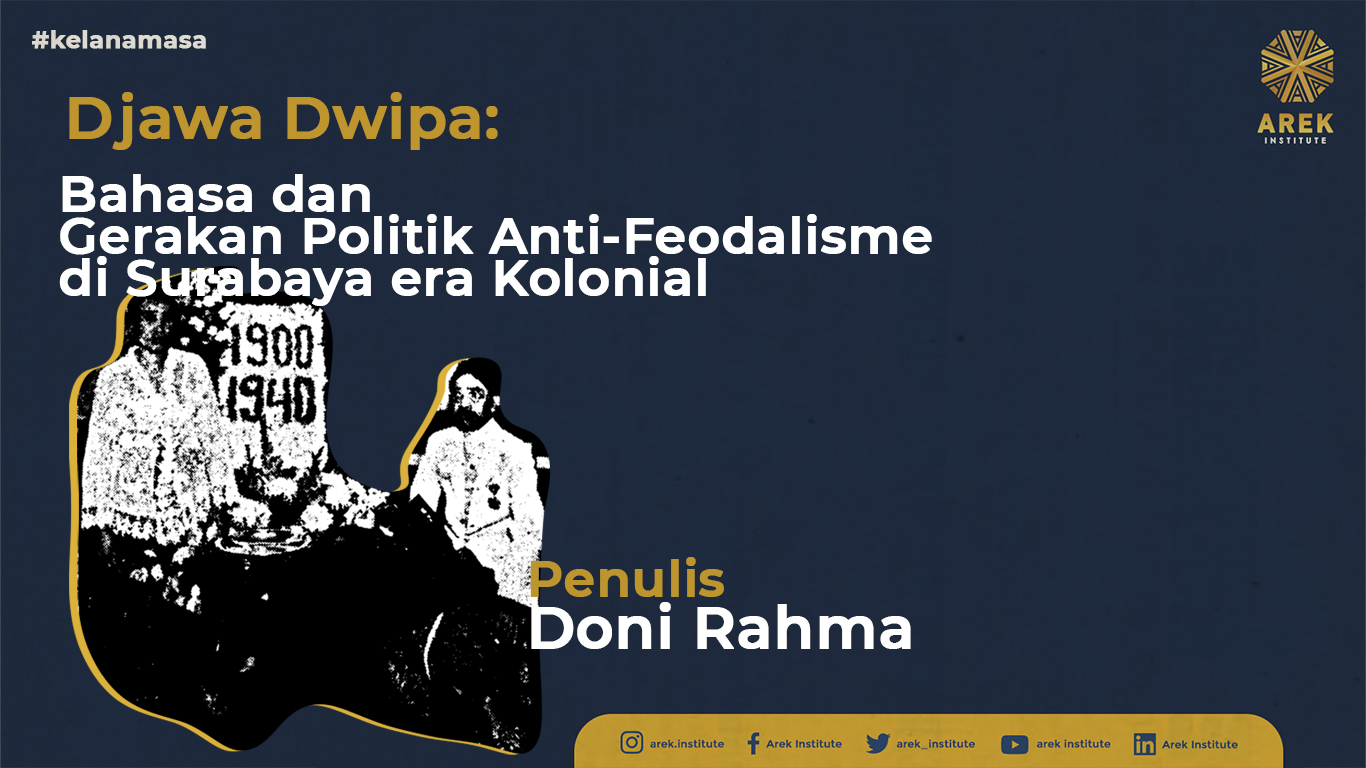

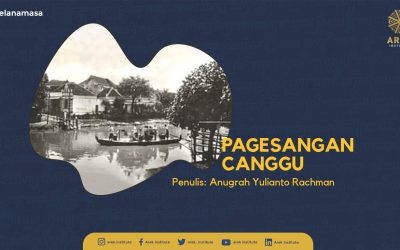
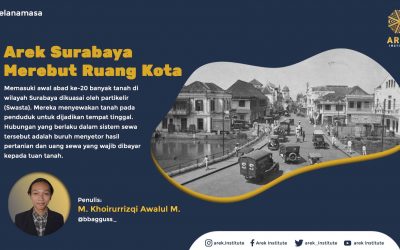

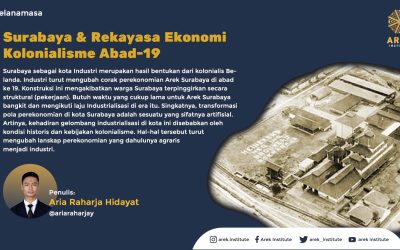
0 Comments